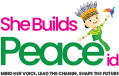Dilahirkan di Blora Cepu 42 tahun yang lalu, Kustiah menganggap perbedaan itu anugerah. Bertetangga dengan orang Kristen mengajarkan dia bertoleransi secara organik. Ditambah dengan sejumlah keluarga menganut ajaran Kristiani, membuatnya keluarganya harus merawat hubungan baik. Di kampung halamannya, toleransi dipraktekkan dan dihidupi oleh keluarganya dan orang-orang di kampungnya sebagai bagian dari merayakan perbedaan. Kunjung mengunjungi di saat peringatan hari besar dan makan bersama tanpa merasa curiga. Indah dan bersahaja. Kustiah pindah ke Cilebut, kabupaten Bogor.
Di sinilah kepekaan Kustiah terhadap perbedaan menemukan tantangan besar. Menjamurya pengajian dan majlis ta’lim yang mengajarkan eksklusivisme beragama, diperkuat dengan sebaran pesan kebencian kepada non muslim oleh media sosial, membuat intoleransi tumbuh subur di wilayah Bogor.25 Desember 2022, sejumlah warga Cilebut melakukan pelarangan ibadah natal, dan viral di media sosial. Kustiah tergerak melakukan sejumlah upaya untuk memenangkan hati dan pikiran para tokoh Nahdatul Ulama.
Akar Keberagaman, Lunturnya Budaya Kebersamaan
Saya mengenal Kustiah sebagai pendamping korban kekerasan terhadap perempuan. Di sebuah grup WhatApps bernama Jaringan Korban Kekerasan Seksual, selama advokasi mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dia terlihat sangat aktif dan antusias dalam merespon kasus-kasus KS yang terjadi di masyarakat. Saya tidak menyangka bahwa dialah salah satu orang kunci dari penyelesaian kasus KS yang menimpa salah satu staf di sebuah Kementerian A di bawah Kabinet Indonesia Bersatu. Saya kagum dengan sepak terjangnya yang tidak mengenal menyerah. Tidak heran, penanganan kasus KS di Kementerian A terjadi tahun 2022, berujung dengan reformasi birokrasi yang peka terhadap KS, dengan membangun sistem pencegahan dan penanganan KS.
Rupanya kepedulian Kustiah diasah dari keluarganya yang memiliki landasan Ke-NUan yang kuat. Tiga nilai NU yaitu Tawassuth (moderat), I’tidal (keadilan); Tasamuh (toleransi), Tawazun (seimbang), mengalir dalam dirinya sangat kuat, dan bahkan mengakar dalam memorinya. Di masa kecilnya, Kustiah tidak merasa aneh dengan orang yang berbeda agama, karena dia memiliki sejumlah keluarga hidup di sekitarnya, menganut ajaran yang berbeda. Setiap hari Minggu, keluarga Kristiani ini melewati depan rumahnya untuk menuju gereja, yang juga tidak jauh dari kampungnya. Suara lonceng gereja sama familiarnya dengan suara bedug dari dalam Masjid. Bahkan sampai saat ini, memori Indah perayaan lebaran, dimana keluarganya dan juga orang-orang di kampungnya saling kunjung ke rumah-rumah tetangganya, termasuk rumah-rumah keluarga Kristiani.
Ibu seorang pedagang dan ayah seorang petani, mengajarkan dengan perilaku bagaimana menghormati tetangga yang beda agama. Perempuan berdarah Blora pernah berpikir menjadi diplomat. Dengan keahliannya dalam bahasa Inggris, kini justru dia menjadi advokat bagi korban kekerasan berbasis gender. Saat ini selain menjadi pengurus RT, dia aktif di salah satu badan otonom Nahdatul Ulama bernama Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKK NU). Meskipun di tingkat nasional, sepak terjangnya begitu dikenali di jaringan NGO, Kustiah memilih untuk mengabdi di masyarakat melalui kerja-kerja akar rumput untuk memperkuat nilai-nilai NU sebagai rumah bersama.
Dukungan Penuh suaminya, membuat Kustiah menemukan ruang tak terbatas untuk peduli kepada sesamanya. Hampir setiap hari, dia menerima tamu, para korban kekerasan terhadap perempuan, yang meminta pertolongannya untuk menyelesaikan kasus. Ketulusan hatinya dan panggilan jiwa sosialnya, menjadi magnet bagi para korban maupun penyintas kekerasan terhadap perempuan.
Nilai Toleransi dan Pergeserannya
Pindah ke Cilebut, Bogor, adalah tantangan bagi Kustiah. Kultur “agamis” dimana simbol-simbol agama begitu kuat dipakai, tidak sejajar dengan keterbukaan dalam menerima perbedaan. Bertebaran ceramah-ceramah yang menyebarkan paham eksklusif, diperkuat dengan kehadiran media sosial dan internet yang membuka akses pada masyarakat, dapat membentuk perspektif intoleransi di masyarakat. Pelarangan ibadah keluarga kristiani, pada natal 2023 merupakan akumulasi sikap intoleransi yang selama ini dimiliki oleh warga. Meskipun dalihnya adalah
Tahun 2015, Setara Institute pernah mengumumkan Bogor merupakan kota dengan indeks toleransi yang rendah. Ini ditandai dengan sejumlah kasus yang terjadi diantaranya adalah pelarangan beribadah jemaat GKI Yasmin (2017), dugaan kristenisasi pada acara gelar budaya di Tugu Monas yang mendorong mobilisasi sejumlah masa (2014), pembubaran sahur on the road, termasuk sejumlah aksi penolakan dan diskriminasi pada pengikut Sunda Wiwitan, Kaharingan, Mahesa Kuring, Gafatar.
Sebagai orang yang dibesarkan dengan nilai toleransi tinggi, Kustiah terpanggil untuk merespon praktik intoleransi di sekitarnya. Memori hidup rukun dengan yang berbeda yang pernah diukir selama masa kecilnya, mendorongnya melawan dengan cara-cara santun dan menggunakan budaya lokal. Dia sangat yakin bahwa para orang tua dan Kyai/Nyai di organisasi NU selalu mengedepankan menghormati yang berbeda. Sebagai Gusdurian, Kustiah mencontohkan bagaimana Gus Dur, memberikan tauladan praktik beragama inklusif, dimana agama tidak boleh menjadi sekat dalam interaksi sosial.
Meskipun tidak ada riset langsung menyorot tentang pergeseran nilai toleransi di Kota Bogor, tetapi Riset yang dilakukan oleh Communication Research Center (CRC) di Universtias Indonesia menemukan penggunaan media sosial, khususnya Facebook berkorelasi kuat dengan peningkatan intoleransi pada kelompok minoritas (2018). Penelitian ini diamini oleh temuan Freedom Institute dan Indonesian Survey Institute (ISI) pada tahun yang sama juga mendapati bahwa pengguna aktif media sosial cenderung lebih intoleran terhadap kelompok minoritas seperti LGBT dan kelompok agama yang berbeda. Tahun sebelumnya, UNESCO telah lebih dulu melansir hasil risetnya tentang penggunaan media sosial yang memperkuat stereotip kepada kelompok minoritas.
Sepertinya temuan riset di atas berkorelasi dengan fenomena baru kecenderungan grup-grup WhatsApp (WA) menyebarkan konten-konten yang intoleransi, termasuk group WA para pengurus NU di Cilebut. Kustiah tidak jarang harus meluangkan waktu untuk melakukan counter terhadap berita-berita palsu yang disebarkan di grup NU. Suatu saat ketika dia mendapatkan postingan seorang perempuan mualaf yang menjelek-jelekkan agama Kristen, dia segera melakukan penelusuran di mesin tracking untuk mencari tahu siapa perempuan tersebut. Temuannya adalah perempuan tersebut baru masuk Islam. Kustiah merespon dengan cara positif seperti ini “Kyai..saya yakin ajaran NU tidak begini. Menurut saya pengetahuan tentang keislaman Ketua NU kita jauh lebih bagus, mengapa harus orang yang baru masuk Islam untuk mengajarkan keislaman? Ketua kita bisa jadi tauladan,”.
Membaca Kerentanan di Masyarakat
NU rasa FPI. Demikian Kustiah menggambarkan bagaimana cara berpikir orang-orang di sekitarnya. Meskipun secara kultural, banyak orang menjalankan amalan NU, tetapi secara pemikiran masih kuat dipengaruhi oleh Front Pembela Islam (FPI). Figur Habib Riziq memiliki pengaruh kuat pada semua lapisan masyarakat, termasuk para pengurus NU di cabang dan ranting.
Hadirnya media sosial dan internet sangat berpengaruh kepada cara pandang warga terhadap perbedaan. Kustiah mencontohkan bahwa di grup WA para kyai saja, banyak individu yang sering melakukan posting-posting informasi terkait dengan intoleransi, tanpa dicek terlebih dulu. Celakanya sejumlah berita ini dimakan mentah-mentah oleh anggota group. Meskipun ini levelnya kyai. Ini menggambarkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih rendah.
Institusi keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering menjadi pembenar atas sikap intoleransi masyarakat. Bahkan NU yang di nasional menjadi garda terdepan dalam gerakan anti radikalisme, di tingkat bawah sering terombang-ambing dengan kegamangan sikap sejumlah anggotanya, bahkan sejumlah individu di dalam struktur pengurus, yang cenderung mengarah ke konservatif. Misalnya saja kasus pelarangan ibadah yang dilakukan di sebuah rumah warga kristiani, sikap NU dan MUI hampir mirip menyepakati aksi warga yang melarang ibadah di rumah karena bukan peruntukan ibadah.
Mungkin tidak saja institusi keislaman yang masih memiliki cara pandang konservatif, tetapi aparat pemerintah desa yang seharusnya tegak lurus pada konstitusi, yaitu memberikan perlindungan kepada semua warga untuk secara bebas menjalankan agama dan kepercayaannya. Dalam kasus pelarangan ibadah natal tahun lalu, justru sikap kepala desa terkesan mengikuti sikap warga yang melakukan aksi pelarangan.
Pada tahun 2010, pernah terjadi sebuah kasus penolakan non muslim, khususnya China, untuk tinggal di RT dekat perumahan yang dihuni Kustiah. Ketua RT tegas menyatakan bahwa ”maaf di RT kami tidak boleh ada Chinese tidak boleh ada non muslim ini rumahnya orang Islam”. Ini artinya pengerasan identitas di masyarakat sudah lama terjadi, dan terekspresikan dalam sikap-sikap eksklusif di masyarakat.
Dikepung dengan sikap intoleransi dari sejumlah institusi agama dan negara, Kustiah lebih mengambil pendekatan kultural dalam membuka perbincangan masalah pelarangan ibadah natal. Menurutnya pendekatan kultural tidak terkesan menggurui, lebih informal, dan mengarah pada perbaikan relasi antar aktor.