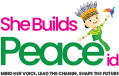“Sebenarnya, saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Ketika saya menyuarakan nilai-nilai keberagaman dan toleransi, saya akan keluar dari ketakutan dan saya akan merasa aman. Perasaan inilah yang ingin saya bagi ke teman-teman yang lain. Kalau kata orang untuk apa repot-repot, biarkan saja polisi yang bergerak dan mengamankan. Saya akan membalasnya dengan candaan, ya memang biarkan saja polisi yang menjaga keamanan, tetapi kita yang menjaga silaturahmi.”
Kira-kira begitu jawaban Yohana ketika ditanya apa yang memotivasinya untuk terus bergerak menyuarakan nilai-nilai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Pernah menjadi korban tindakan intimidatif dari beberapa kelompok intoleran membuatnya tergugah untuk keluar sindrom minoritas. Yohana tidak mau hanya duduk berpangku tangan dan terus-terusan menjadi korban, dia juga ingin ambil peran dengan memberdayakan diri dan orang-orang di sekitarnya dengan mengkampanyekan nilai-nilai toleransi dan keberagaman.
Yohana dan Dinamika Mayoritas Minoritas
Mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya di benak Yohana kecil bahwa dia akan mengalami tindakan intoleransi yang intimidatif. Pasalnya, Yohana dibesarkan dalam lingkungan homogen di mana Kristen menjadi agama mayoritas. Di sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan yaitu Tanah Toraja, Yohana menghabiskan masa kecilnya dengan damai bersama kerabat dan tetangga yang mayoritas Kristen.
Selepas SMA ia memutuskan pergi ke kota Makassar untuk melanjutkan kuliah; barulah Yohana bertemu dunia baru. Di lingkungan barunya, Yohana bukan lagi menjadi bagian dari kelompok mayoritas. Yohana mengaku shock karena mengalami perbedaan dari kehidupan sebelumnya yang diliputi kemudahan dan kenyamanan, sekarang Yohana menghadapi diskriminasi hanya karena dia bukan bagian mayoritas.
“Ketika kuliah dulu saya pernah kena yang namanya sweeping KTP, walaupun tidak sampai mengalami kekerasan fisik tetapi tetap saja menyisakan trauma mendalam. Saya melihat teman saya dibentak-bentak dan diancam. Sebagaimana teman-teman yang lain saya pun merasa terancam dengan tindakan intimidatif tersebut,” ujarnya.
Aksi sweeping KTP oleh para mahasiswa Makassar tersebut dilatarbelakangi gempuran Amerika Serikat ke Afganistan, dan sebaliknya aksi serupa untuk menggalang kekuatan mengecam Amerika Serikat dan membela umat Muslim. Namun sayangnya, solidaritas terhadap masyarakat Muslim dilakukan dengan melakukan intimidasi terhadap para pemeluk kepercayaan lain. Semua orang dicegat di jalan dan ditanyai, “Anda agamanya apa?” dengan ekspresi yang sangat mengintimidasi.
Dari pengalaman traumatik itulah akhirnya Yohana dipenuhi dengan prasangka-prasangka negatif terhadap kelompok agama mayoritas. Prasangka tersebut yang kemudian menjadikannya pribadi tertutup, takut, ragu-ragu dan khawatir. Yohana bercerita bahwa dia menjadi sangat tertutup apalagi terhadap teman-teman yang berbeda di tahun-tahun awal kehidupannya di kampus.
Membuka Diri, Memilih Berdaya
Bergabung dengan organisasi Kristen di kampus menjadi titik awal Yohana menemukan jalan untuk membuka diri. Lewat organisasi tersebut Yohana mau tidak mau berinteraksi dan berdialog dengan banyak teman lintas kampus.
“Pelan-pelan saya mulai dapat jalan untuk membuka diri, dan pelan-pelan juga segala prasangka yang ada di dalam diri saya bisa terurai. Lalu sekian tahun setelah itu setelah mengikuti berbagai dialog dari organisasi pemuda Katolik lalu saya bergabung dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel yang didalamnya terdapat organisasi keagamaan maupun non keagamaan. Dari situlah pemikiran saya semakin terbuka,” ujar Yohana menceritakan proses transformasinya
Pemikiran terbuka itu semakin menguat terlebih saat Yohana bergabung di komunitas lintas iman. Sebuah jaringan kultural yang diberi nama Jalin Harmoni.
“Dalam komunitas ini saya bertemu dengan berbagai kelompok yang berasal dari berbagai agama dan aliran kepercayaan. Saya bertemu dengan orang-orang yang senasib dengan saya, pernah menjadi korban Tindakan intoleransi. Di situ juga saya berdialog dengan teman-teman lintas iman dengan sangat terbuka sehingga saya sampai pada titik bahwa ternyata segala prasangka negatif saya selama ini adalah salah,” lanjutnya.
Yohana menceritakan sebenarnya secara umum masyarakat kota Makassar sangat rukun. Dalam kehidupan bertetangga juga saling menghargai dan menghormati. Dalam lingkungan sekitar rumahnya, walaupun Kristen menjadi agama minoritas, penganut agama lain tetap berlaku baik dan bertoleransi.
Tetapi anehnya jika sudah membawa nama kelompok, masyarakat Makassar mudah sekali terprovokasi. Apalagi sekarang informasi sangat mudah tersebar melalui media sosial dan sayangnya seringkali informasi tersebut adalah informasi yang salah dan sarat ujaran kebencian.
Sungguh suatu keadaan yang menurut Yohana sangat paradoksal; di kehidupan sehari-sehari tiap individu baik-baik saja, tetapi jika sudah membawa nama kelompok masyarakat gampang tersulut. Inilah kemudian yang menjadi keresahan selanjutnya dan membuat Yohana bertanya-tanya, “Kenapa ketika hari raya keagamaan gereja harus dijaga oleh polisi? Padahal kalau dilihat relasi secara individu baik-baik saja.”
Di titik itulah Yohana merasa penting membagi apa yang diketahuinya tentang nilai-nilai toleransi dan keberagamaan kepada masyarakat umum. “Kampanye terus menerus tentang isu tersebut penting dilakukan untuk membentengi masyarakat dari serangan paham-paham yang radikal dan intoleran. Karena sebenarnya kelompok toleran itu lebih banyak, lebih mayoritas. Hanya saja seringnya kalah langkah daripada mereka yang intoleran,” ujarnya lagi.
(bersambung)
***
Kisah Yohana Lobo selengkapnya beserta perempuan perdamaian lainnya didokumentasikan oleh AMAN Indonesia bersama She Builds Peace Indonesia dalam buku She Builds Peace Seri 1: Kisah-Kisah Perempuan Penyelamat Nusantara.
Banyak pembelajaran tentang agensi perempuan yang bisa ditemukan dengan membaca semua cerita di buku ini. Untuk mendapatkannya, bisa dipesan melalui link berikut bit.ly/pesanbukuSBPseri1.