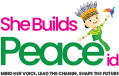Judul buku : Gincu Sang Mumi
Penulis : Tamura Toshiko
Terjemah : Asri Pratiwi Wulandari
Penerbit : Mai
Jml.hlm :128
Thn.cetak : 2022
ISBN : 978-623-7351-93-1
Membaca buku ini, pada mulanya saya berpikir bahwa novel yang latar cerita Jepang sangat berbeda dengan kondisi perempuan Indonesia. Namun, penulis melihat secara spesifik tentang eksistensi perempuan dalam karya sastra. Tidak hanya di Jepang, kondisi kesusasteraan Indonesia belum banyak memberikan ruang bagi perempuan. Karya sastra yang diangkat oleh perempuan banyak dianggap tidak memiliki kebaruan dan orisinalitas dalam setiap tema yang ditulis.
Anggapan semacam ini kemudian meminggirkan peran perempuan dalam karya yang sudah ditorehkan. Kalau kita baca beberapa sastrawan di Indonesia, jarang sekali untuk melihat perempuan dunia sastra dengan mahakarya yang sudah ditorehkan. Peminggiran perempuan ini berakibat pada absennya posisi perempuan sebagai sastrawan yang bisa menjadi panutan bagi semua orang. kenyataan semacam ini tergambar jelas dalam kisah yang diperankan oleh kisah Minoru bersama suaminya yang bernama Yoshio.
Keduanya adalah sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan, melarat dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profesi menulis yang ditekuni oleh suaminya tidak menciptakan kelayakan hidup bagi keduanya. Masalah ini berakibat fatal terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun. Dalam konteks ini, sebagai pembaca, kita dapat memahami betul bahwa dalam dunia kepenulisan ternyata tidak membuat seseorang menjadi kaya.
Jangan kaya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tidak bisa. Namun, cerita yang paling layak untuk dibicarakan dalam tulisan ini bukan soal kelayakan hidup para penulis. Akan tetapi, posisi Minoru sebagai seorang istri. Karena hidup dalam kemiskinan, Yoshio kemudian memaksa Minoru untuk mencari pekerjaan supaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga itu.
Sebenarnya, Minoru memiliki kemampuan menulis yang sangat bagus. Akan tetapi, pengalaman pahitnya membuat dirinya tidak percaya dengan kemampuan menulisnya. Hingga pada suatu hari, Yoshio mendesak Minoru untuk ikut serta dalam sayembara novel. Dalam kondisi tersebut, Minoru menolak untuk mengikuti lomba tersebut karena ketidakpercayaan diri. Baginya, menulis adalah pekerjaan yang tidak boleh dipaksakan. Minoru tidak menikmati sebuah seni, melainkan terjun dalam perjudian.
“Kekesalan Minoru menggelegak di perut ketika ia memikirkan Yoshio yang mencoba menggiringnya melakukan seni yang seperti perjudian, sementara lelaki itu sendiri sama sekali tak tahu cara membiarkannya menikmati seni (hal. 50).”
Namun karena desakan sang suami, hingga ancaman berpisah, akhirnya ia kemudian menyerahkan naskahnya dalam perlombaan tersebut. Kondisi sulit keduanya mengakibatkan pertengkaran dan perpisahan menjadi pilihan yang harus dilakukan. Akan tetapi nasib baik berada di pihak keduanya. Ternyata sayembara tersebut dimenangkan oleh Minoru dan keduanya bisa bertahan hidup dengan uang hadiah dalam beberapa waktu.
Disinilah posisi Minoru yang menanggung paksaan dari sang suami. Ia tidak menikmati seni yang menjadi salah satu kesukaan. Melainkan karena keterpaksaan dari desakan sang suami. Dalam kisah ini pula, digambarkan secara detail bagaimana posisi Minoru yang dianggap tidak baik. Hal ini tergambarkan dalam sebuah cerita ketika Minoru memenangkan juara tersebut, Yohio justru merasa bahwa kemenangan tersebut berkat dirinya karena sudah mendesak Minoru untuk mengikuti sayembara itu. Artinya, jika tidak didesak olehnya, kemenangan tersebut tidak akan terjadi.
Disinilah pembaca diajak untuk berpikir posisi perempuan yang diperankan oleh Minoru. Pertama, Minoru hidup dengan keterpaksaan. Kedua, kemampuannya justru tidak dilihat dan tidak diapresiasi, justru bukan dianggap semua kemampuan, melainkan kinerja sang suami. Kenyataan ini diperkuat dengan penjelasan salah satu juri laki-laki yang menyeleksi karya yang masuk kepadanya.
Baginya, karya yang dihasilkan oleh Minoru bukanlah yang terbaik. Sebab, ia yang berperan untuk memenangkan Minoru karena kenal dengannya. Disinilah Minoru berada dipersimpangan kegalauan akan kemampuan yang dimilikinya. Hasil kerja kerasnya dalam menyelesaikan naskah tidak berarti apa-apa, jika dibandingkan dengan peran para laki-laki yang mendaku sebagai orang paling berjasa dalam kemenangan novel tersebut.
Cerita tidak berhenti pada kemenangan tersebut. Suatu hari, Minoru mendaftar sebagai aktris utama dalam sebuah kelompok seni. Karena parasnya yang tidak memenuhi standart kecantikan, kemampuannya dalam memerankan sebuah tokoh adalah hambatan yang utama. Tidak hanya kelompok seni dalam lingkaran tersebut yang mencaci tampang Minoru, bahkan sang suami, Yoshio juga mengakui kejelekan istrinya. Ia juga melarang istrinya untuk bergabung dalam kelompok seni tersebut karena merasa malu kepada teman-temannya memiliki istri yang jelek.
“Meski memiliki kekuatan seni bak intan, seorang aktris tidak akan dianggap memesona jika tidak memiliki rupa laksana bunga (hal. 88).”
Gambaran ini adalah sebuah pertanda bahwa, dunia seni yang selalu menyoroti kreativitas, kemampuan memerankan lakon. Hingga menekuni alur cerita yang disampaikan. Tidak ada harganya ketika dibenturkan dengan tampang yang tidak memenuhi standart kecantikan. Fenomena ini adalah kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Dunia sastra belum memberikan ruang luas bagi perempuan. Eksistensi perempuan dikaburkan dengan budaya patriarki yang masih menganggap bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak memiliki kemampuan kebaruan dalam karya.