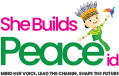Bapak selalu bilang saat saya bersepeda bersamanya melewati perkampungan kumuh. “Kita ini hidup di negara yang gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa masih banyak orang hidup miskin? Apa kamu bisa mencari jawabannya.” Perkataan itu mendorong saya selalu berpikir keras. Apa sebenarnya yang menyebabkan kemiskinan? Mengapa terjadi kesenjangan dalam masyarakat?
Masa kecil Sri Wahyaningsih, lahir di Klaten, 19 Desember 1961, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan itu. Wahya (demikian dia dipanggil) dibesarkan dalam keluarga yang dikelilingi ratusan pekerja usaha yang dikelola ayahnya sebagai pengusaha lurik, batik dan omprong tembakau (usaha mengoven tembakau menjadi lembaran kering bahan cerutu). Belum lagi Simbah (kakek) yang bekerja menebas padi.
Keseharian Wahya kecil tumbuh bersama anak-anak pekerja, dikelilingi orang memotong padi dengan ani-ani (alat pemotong padi), menumbuk padi dengan lesung, menyunduk tembakau dan menenun lurik. Wahya dibesarkan tanpa dibeda-bedakan. Relasi Wahya dan saudaranya yang lain beserta anak-anak dan keluarga pekerja sudah layaknya keluarga sendiri.
Apalagi Bapak, Ibu, Simbah tak pernah membeda-bedakan baik makanan maupun berpakaian. “Bapak saya sering membelikan baju yang sama untuk semua anak. Simbah saya juga menyediakan makan untuk kami semua,” kisahnya.
Pengasuhan itu membuat Wahya belajar bertoleransi, tanpa mementingkan status sendiri, apakah posisi saya dari keluarga pengusaha atau pekerja. Oleh sebab konsep toleransi yang diajarkan keluarganya, Wahya menjadi sosok yang kritis dengan apa yang terjadi. Misal dia selalu menolak memakai perhiasan saat bersama dengan teman-teman yang tidak menggunakan perhiasan.
Sebagai anak pengusaha, Wahya dan saudaranya juga punya pengasuh masing-masing, satu anak satu pengasuh. Namun, hubungan mereka dan para pengasuh satu sama lain sudah seperti saudara. Pengasuh mereka sangat penyayang dan penuh perhatian, kata Wahya.
Jika habis gajian, anak-anak asuhan mereka itu kerap dibelikan mainan dan makanan. Hal itu membuat Wahya keheranan, mengapa para pengasuh ini bekerja untuk keluarganya, tetapi bayarannya tak segan digunakan untuk mentraktir dia dan ketiga saudaranya. Tanpa tahu jawaban sesungguhnya, tindakan sederhana itu malah jadi salah satu pendorong sikap Wahya bersaudara untuk ikut peduli dengan sesama.
Beranjak SMA, Wahya melanjutkan di Yogyakarta. Sikap kritis dan kepedulian kepada sesama itu makin terasah di kota yang lebih besar dari kampung halamannya di Klaten. Di sekolah, ia menjadi pengurus OSIS, lalu turut serta dalam kegiatan remaja kampung. Berbagai permasalahan masyarakat kota besar yang ditemui tak sesederhana daerah asal Wahya.
“Ada peristiwa yang sangat mengejutkan dan membuat syok ketika saya melihat gelandangan yang tidur di emperan toko/rumah kosong dan mengais-ngais tong sampah mencari sisa makanan yang dibuang orang. Semiskin-miskinnya di desa, tak berpunya pun kami masih makan nasi dan lauk dari tetangga, tidak sampai ada yang mengais-ngais, mencari di tempat sampah. Tidur pun, ya di rumah, sekalipun sangat sederhana. Kalau sampai tidak punya, masih bisa menumpang di rumah tetangga. Seperti rumah saya, banyak juga pekerja Bapak dan Simbah yang tidur dan tinggal di rumah,” ujar Wahya dengan wajah menunjukkan keprihatinan.
Pengalaman pertama menyaksikan hal itu sungguh meresahkan hati Wahya. Peristiwa ini dia sampaikan ke teman-teman sebaya sekolahnya, sayangnya mereka tak memberi tanggapan. Akhirnya ketika pulang kampung, dia mencurahkan kesedihannya kepada Bapaknya. Tanpa diberi jawaban memuaskan, Bapak malah memberi tantangan kepadanya, apa yang dapat dilakukan seorang Wahya untuk menolong mereka.
“Saya berpikir keras, lalu membawa keresahan itu ke teman-teman persekutuan doa di tempat kosan saya di Yogya. Puji Tuhan mereka memberi respon bagus, segera saya wujudkan saja langkah-langkah kolaborasi dengan mereka.”
Wahya dan teman-teman mulai membuat acara pekan masak untuk mencari dana yang akan didonasikan untuk para gelandangan. Selain pekan masak mereka juga mengumpulkan barang-barang bekas seperti koran, botol untuk dijual. Setelah terkumpul sejumlah uang mereka belikan makanan untuk dibagikan. Mereka pun giat mengumpulkan pakaian bekas pakai yang masih pantas untuk disumbangkan.
Selain itu, Wahya dan teman-teman persekutuan doa mulai membuka ruang dialog dan rutin menjalin interaksi dengan para gelandangan. Dia menceritakan, ada gelandangan yang masih nyambung ketika diajak bicara. Namun, ada juga yang sudah tidak bisa menangkap pembicaraan. Sungguh sebuah kenyataan sedih dari kemajuan dunia perkotaan.
Dari bincang-bincang tersebut, Wahya dan teman-teman mengetahui jika para gelandangan dulu adalah orang-orang desa yang bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, tidak mencapai keberhasilan. Ketika mereka kemudian pulang kembali ke Jawa, rumah, tanah, sawah, kebun semua sudah tak ada, habis dijual. Tak ada yang dimiliki, nasib mereka pun berujung menggelandang.
Interaksi Wahya dengan para gelandangan inilah yang kelak menuntun dan membuka ruang perjumpaan dengan Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, atau dikenal dengan Romo Mangun. Seorang pastur yang mendedikasikan diri melayani orang-orang pinggiran. Wahya berkisah, Romo Mangun tidak hanya berhenti di kata peduli.
Namun, Beliau betul-betul membersamai, sampai ikut tinggal di Lembah Code (bantaran sungai Code) berbaur dengan kaum papa tersebut. Romo kemudian membangun rumah-rumah sederhana yang sengaja dibuat artistik di bantaran sungai tersebut, untuk menggantikan rumah-rumah kardus sebelumnya. Hal itu bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak sebagai manusia. Bukankah hal itu merupakan awal dari upaya memanusiakan manusia?
Membersamai masyarakat Kali Code, mempertemukan Wahya berhadapan dengan banyak konflik. Ada Peristiwa Code, di mana orang -orang Code digusur pemerintah dengan alasan area tempat tinggal mereka akan dibangun sabuk hijau perkotaan. Nasib masyarakat Code saat itu seketika menjadi tidak jelas, karena akan dipindahkan di pinggiran yang jauh dari sumber penghidupan mereka.
“Romo Mangun juga melakukan mogok makan sebagai unjuk protes. Saya dan teman-teman ikut mendukung gerakan Romo Mangun, “kisahnya. “Konflik yang lain mungkin banyak yang sudah dengar juga. Peristiwa Kedung Ombo, dimana pemerintah menggusur masyarakat Kedung Ombo, mengambil alih lahan tempat tinggal mereka untuk dijadikan waduk. Ganti rugi memang diberikan, tetapi dalam jumlah yang sangat tidak layak. Kesewenang-wenangan itulah yang Romo dan kami lawan dengan demo.”
Konflik-konflik yang lain, mendorong Wahya muda berani ikut dalam rombongan demo ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). wahya meyakini adanya bukti pungli dan pemerintahan yang melakukan tindak korupsi. Tak berbanding lurus dengan pendidikan lanjutannya di Akademi Keuangan dan Perbankan, yang diasumsikan tidak berelasi dengan gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan, Wahya tak henti bersikap kritis.
Dia melanjutkan perjuangan dengan aktif sebagai relawan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa serta menjadi pengurus Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), khusus untuk menjadi tenaga pendamping kelompok tunawisma. Kerja-kerja kemanusiaan inilah yang berulang kali membuka ruang perjumpaan dengan sang calon suami, mendiang Kresnawan Buddhanto. Seorang biarawan kristen di Taize Community Perancis yang kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi Teologi di UKDW.
Keduanya saling cocok setelah pertemuan dan kerja kemanusiaan tersebut, yang berujung ke jenjang pernikahan. Perjuangan pasangan dua aktivis isu kemanusiaan ini pun tak berhenti di kota Gudeg. Keduanya, berlanjut hingga pelosok Sumatera, dengan isu kemanusiaan yang lebih kompleks dan tantangan yang lebih berat.