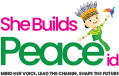Lahir dan dibesarkan oleh orangtua yang menjunjungkan kesetaraan dalam hubungan. membuat Mona Eltahawy, seorang jurnalis kenamaan Mesir-Amerika dan Founder ‘Feminist Giant’, menikmati banyak privilese sebagai perempuan. Ia dan saudara laki- lakinya tak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mereka sama-sama memperoleh hak penuh sebagai anak, dan dibesarkan secara optimal oleh ayah ibunya.
Melalui masa kecil yang cenderung demokratis di Mesir dan Inggris, Mona baru menyadari perbedaan mencolok ketika keluarga mereka pindah ke Arab Saudi di usianya yang menginjak 15 tahun. Di sana, ia mulai ‘diperlakukan’ berbeda sebagai perempuan. Hal yang membuat ia tercengang sekaligus berpikir keras: mengapa budaya di Saudi bisa berbeda dibandingkan dengan Mesir? Padahal mayoritas penduduknya sama-sama Muslim. Di situlah ia menyadari bahwa Islam memang satu, tapi praktiknya sangat beragam dari satu negara ke negara lain.
Islam di tanah kelahirannya, Mesir, memiliki praktik yang berbeda dengan yang diaplikasikan di Arab Saudi, yang menurutnya cenderung membatasi pergerakan perempuan. Yang menarik, setelah ia mengalami gegar budaya di negara baru, ia tak lantas diam saja. Di perpustakaan sebuah kampus di Jeddah, ia malah ditakdirkan ‘bertemu’ dengan Nawal El Saadawy dan Fatima Mernissi lewat buku-buku mereka. Perjumpaan Mona dengan pemikiran yang ditawarkan oleh Nawal dan Fatima selanjutnya membentuk pribadi Mona Eltahawy hingga saat ini.
Meski di awal-awal membaca buku mereka, ada perasaan takut jika mengiyakan argument feminis-feminis tersebut, nanti ia akan dijauhi oleh komunitas sekitarnya, dan dianggap berbeda. Namun, alih-alih berhenti membaca karena takut. Ia justru semakin ketagihan untuk meneruskan halaman demi halaman yang tak henti menghipnotisnya untuk membuka mata lebih luas terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh kaum perempuan terutama di kawasan Timur Tengah.
Bagaikan oase di padang padir yang tandus, semua pertanyaan yang ada di kepalanya mendadak terjawab dengan pernyataan-pernyataan lugas dalam buku Nawal dan Fatima, yang hingga kini masih menjadi inspirasi utamanya dalam menulis. Menginjak dewasa, kegiatan aktivismenya dalam menyuarakan isu-isu perempuan semakin kuat. Terlebih sejak awal revolusi Mesir 2011, Eltahawy tak berhenti menulis, berbicara, dan menge-tweet tanpa henti di akun media sosialnya yang memberikan ulasan dari berbagai peristiwa di Mesir dan negara-negara tetangganya dari perspektif feminis kepada audiens di seluruh dunia.
Baginya, Arab Spring merupakan momen penting dengan beragam gejolak politik: penggulingan kekuasaan diktator di berbagai negara; implementasi konstitusi sementara yang belum terlihat efektivitasnya; pemberontakan rakyat melawan pemerintah militer; serangan seksual terhadap pengunjuk rasa (termasuk Eltahawy) oleh pasukan keamanan Mesir; hingga pembantaian sipil dan pemilihan parlemen. Meski tujuannya adalah perubahan sistemik negara ke arah yang lebih baik.
Sayangnya, Arab Spring hingga kini belum sepenuhnya membuahkan hasil baik, terutama bagi kaum perempuan. Dari awal tahun 2011, represi justru semakin meningkat di Mesir dan semakin menghalangi kaum perempuan untuk berkiprah lebih luas dari kehidupan publik dan politik. Merujuk pada catatan Dalia Fikry Fahmy, yang juga anggota dari the Egyptian Rule of Law Association, sejak 2013, pemerintahnya telah menahan lebih dari 2.000 wanita, dan 92 telah terbunuh.
Kelompok perempuan pembela hak asasi manusia bahkan menghadapi intimidasi, pelecehan yudisial, penangkapan sewenang-wenang, hukuman berat, dan dipenjara. Saat mereka melawan, senjata terakhir yang dilakukan oleh pasukan militer adalah melecehkan mereka secara seksual. Pemerkosaan seakan dijadikan protokol negara untuk membungkam perempuan. Akibatnya, para aktivis yang lantang berjuang kemudian mengalami beban ganda.
Tak hanya itu saja, jumlah tahanan politik perempuan terus meningkat, saat ini diperkirakan lebih dari 40.000 individu. Yang miris, LSM yang menjalankan fungsi untuk memantau, melaporkan, dan membantu para wanita ini kemudian ditutup paksa oleh negara. Itu baru di Mesir, di negara-negara Timur Tengah lainnya, kondisinya tak jauh berbeda. Status mereka masih dianggap warga kelas dua. Di negara-negara yang masih kesulitan keluar dari krisis seperti Suriah dan Afghanistan, anak-anak perempuan dijual dengan kedok pernikahan. Hak-hak dasar mereka tak signifikan untuk diperjuangkan.
Melihat kondisi tersebut, Mona Eltahawy merasa isu-isu perempuan pada momen Arab Spring malah sengaja dimarjinalkan oleh sistem karena dianggap tidak penting. Ketika para aktivis turun ke jalan atau menyuarakan hak-hak mereka dan generasi penerus, pelabelan negatif dari pemerintah malah makin kencang. Para pejuang hak-hak perempuan ini dicap ‘too loud, swears too much, and goes too far’. Stigmatisasi ini sengaja dilanggengkan agar perempuan lain menjadi takut bersuara. Walau di beberapa negara, ada kebijakan baru untuk menambah kuota perempuan dalam politik, nyatanya hal itu belum menjadi panacea untuk mengatasi dampak buruk system patriarki di sana.