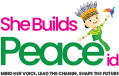Ketika di awal, MorisDiak memang perjalanan personal Mila dalam proses penyembuhan dan pemulihan diri dari berbagai masalah hidupnya. Sewaktu mengeksplorasi tenun, selain semangat kolaborasi yang menjadi brand value produk tersebut, dia merasa ikut memperkenalkan identitas budaya dari kedua putrinya yang berdarah Savu-Timor.
Mila membeli tenun langsung dari daerah asalnya, salah satunya dari komunitas Lakoat Kujawas, kewirausahaan sosial di Mollo, yang banyak melakukan pendampingan penenun termasuk usia remaja untuk keberlanjutan tradisi tersebut. Alasan Mila dan MorisDiak berinteraksi dengan komunitas tenun, agar mereka dapat terus berkarya, bisa diapresiasi lebih banyak orang dan tentunya bermuara pada pelestarian budaya.
Fatunausus, salah satu seri backpack produksi awal MorisDiak dan merupakan karya komunitas Lakoat Kujawas memiliki kisah sendiri dalam dunia tenun. Fatunausus yang artinya batu menyusui itu, diambil dari nama tempat yang menjadi saksi sejarah kemenangan rakyat Mollo mengusir penambang marmer dengan cara menenun di lokasi.
Cerita di balik tenun, tak hanya mengejutkan seperti kisah Fatunausus saja. Mila menuturkan, dahulu menenun menjadi syarat utama bagi seorang untuk dapat menikah. Alasannya dengan begitu seseorang terlihat mampu memenuhi kebutuhan sandang keluarga. Namun, lama kelamaan syarat itu memudar, meski dalam prosesi adat pernikahan, tenun masih menjadi salah satu alat tukar sebagai bentuk hubungan kekerabatan.
Dalam tradisi Malaka (Timor bagian Barat), tanah kelahiran kedua putrinya, untuk mahar pernikahan tidak memakai sistem belis seperti di pelosok Timor yang lain. Namun, akan ada proses tukar hantaran sebagai bentuk keterikatan dua keluarga besar, yang di dalamnya juga menuntut kehadiran tenun. Sayangnya, saat ini, ketika tenun sudah bisa dibeli di pasar, mereka menjadi tidak diharuskan menenunnya sendiri.
Perjalanan tenun, MorisDiak dan hidup baik ternyata tak berhenti di Yogyakarta saja. Setelah ibu kandung Mila berpulang di tahun 2019, tak lama kemudian dia memutuskan menyusul suami dan anak-anak yang lebih dulu kembali ke NTT. Tentu dengan harapan bahwa Mila juga tetap bisa mengembangkan MorisDiak dengan kembali ke daerah tersebut.
Diiringi semangat menghubungkan dan mempertemukan dirinya, anak-anak, penenun Timor, para penjahit di Yogya serta tentu saja para konsumen, perjalanan pulang MorisDiak seolah menempatkan brand dan karya tersebut kembali ke kampung halamannya. Tempat dimana MorisDiak beroleh nama dari Bahasa Tetun-Timor Barat, yaitu Hidup yang Baik atau Hidup yang Indah.
Sayangnya, datanglah wabah covid-19. Ketika Mila kembali ke Malaka tahun 2020, rencana awal untuk melanjutkan usaha di NTT, tersandung ketika covid-19 merajalela di Jawa. Toko-toko tempatnya menitipkan produk tutup, asisten yang membantu produksi di Jogja juga terimbas. Sementara untuk berjualan online dari Malaka (NTT), sangat terpengaruh di akses terutama transportasi.
Meskipun bisa dilakukan, tapi biaya pengiriman cukup tinggi dan waktu yang lebih lama. Apalagi, untuk melanjutkan produksi di NTT, Mila terbentur bahan baku lainnya yang sulit didapat, termasuk ongkos produksi yang jauh lebih tinggi. Berhadapan dengan tantangan tersebut, Mila tak patah arang. Dia mengambil langkah lain, memanfaatkan waktu jeda tersebut untuk terus belajar tentang mempelajari pewarna alam dan proses penenunannya. MorisDiak boleh hiatus tapi semangatnya untuk hidup baik tak berarti memudar.
Mulailah Mila belajar, menggali informasi tentang pewarna-pewarna alam yang sudah ditinggalkan, mencari jejaknya, mengumpulkannya, dan bereksperimen dengan bahan-bahan tersebut. Selain itu, dia mengumpulkan alat-alat untuk menenun, mempelajari tekniknya, mendokumentasikan motif-motifnya. Dia pun belajar mengembangkan motif-motif baru dan menuangkannya dalam tenunan pewarna alam yang dibuatnya.
Tentang motif baru ini, Mila memang perlu mengupayakannya karena kebanyakan motif tenun NTT ini sudah dilindungi HAKI (hak kekayaan intelektual dan indikasi grafis) sehingga tidak bisa digunakan secara sembarang oleh orang luar NTT. Apalagi dengan minimum informasi terkait filosofi di balik motif tersebut. Terjun langsung dalam dunia tenun, juga membukakan ruang perjumpaan Mila dengan permasalahan yang dihadapi para penenun.
“Penenun di NTT kebanyakan dikategorikan sebagai pekerja saja, tanpa pemahaman bahwa mereka sesungguhnya adalah pelaku budaya yang sedang menciptakan sebuah karya seni sekaligus melestarikan pengetahuan yang hanya diturunkan secara lisan,” ujarnya mengungkapkan keprihatinan.
Pengetahuan menenun, tambahnya, tidak diperoleh secara terstruktur seperti layaknya mata pelajaran lainnya di sekolah. Hal itu diwariskan secara lisan melalui proses laku yang rumit, tahapan-tahapan yang banyak, tanpa terdokumentasi memadai agar dapat dipelajari masyarakat umum.
Sehingga, ketika sang guru/maestro meninggal, hanya sedikit anak/”murid” yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang akan bertahan meneruskannya. Apalagi kemajuan jaman juga terus menggerus budaya ini. Padahal, mundur ke belakang, era kolonialisme, NTT termasuk dataran Timor lainnya menjadi penghasil kapas terbaik se-Nusantara. Bukankah hal tersebut berarti sumber daya untuk pengembangan potensi tenun tak berkekurangan.
Perempuan dan Penjaga Kelestarian Tenun
Setelah Mila menelusuri perjalanan proses menenun itu, dia makin memahami ketrampilan menenun sesungguhnya tidak semudah yang dibayangkan. Menenun menuntut ketrampilan, ketekunan, kemampuan nalar matematis geometris, memori pengetahuan kimia tentang bahan-bahan dan nilai filosofis di dalamnya, dan masih banyak lagi.
Mila menemukan fakta bahwa ketika seorang perempuan mampu menenun dengan baik, berarti dia sudah melewati tahapan belajar banyak hal tersebut. Sehingga seorang perempuan yang telah mampu menenun, sebenarnya telah melewati proses pembelajaran dan pendewasaan diri yang cukup panjang.
Kemajuan teknologi dan bermunculannya aktivitas kekinian seperti keasikan eksplorasi gadget, maupun keseruan belajar menjadi kreator konten bisa memicu konflik tersirat. Di mana hal tersebut didukung pula kehadiran tekstil print motif tenun dan tenun ATBM yang mengubah konsep dan nilai filosofi tenun sendiri.
Mila mencontohkan tanaman jagung saja bisa menjadi motif yang nenggambarkan tradisi Hamis Batar, perayaan panen jagung, di mana seluruh keluarga besar berkumpul di rumah adat. Perlakuan istimewa pada jagung ini dikarenakan relasi kultural bagi masyarakat adat Malaka, melebihi padi yang kini malah mendominasi bahan konsumsi.
Filosofi motif-motif yang kaya makna itu, termasuk sisa benang yang terurai pada kain tenun yang bermakna ketidaksempurnaan hidup tentu tak akan ditemui dalam kain tenun yang diprint dan diproduksi dalam jumlah massal, termasuk ATBM. Daya tarik kedua tenun hasil kemajuan teknologi ini, tutur Mila tentu lebih kepada nilai ekonomis yang lebih murah sehingga lebih mudah diakses oleh banyak kalangan.
Masalah lebih peliknya, perlindungan hak cipta dan juga perlindungan secara ekonomi, yang masuk dalam HAKI ini belum diajukan maupun lambat diproses, oleh semua regional di NTT, termasuk untuk Kabupaten Malaka. Kewajiban menghadirkan tenun tangan saat upacara-upacara tak menjadi prioritas, apalagi disusul juga dengan kemunculan tenun, dengan berbagai modernisasi teknik pembuatannya.
Tentu hal tersebut akan berpengaruh kepada konsistensi dan keteguhan para penenun yang tinggal di daerah pedalaman ataupun pulau-pulau terluar NTT, dari mulai proses pembuatan hingga pemasaran ke tangan konsumen. Pemasaran online sama halnya dengan keinginan Mila dan MorisDiak itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Biaya relatif mahal dan waktu pelayanan yang lebih panjang, akses internet juga sangat terbatas.
“Bukannya tak ada yang berupaya melestarikan tenun tangan ini , termasuk budaya dan filosofinya. Baik pemerintah maupun komunitas-komunitas. Memang dibungkusnya, pelestarian budaya, tapi pada akhirnya semua terfokus pada pemberdayaan ekonomi, dalam arti bisa menghasilkan. Kalau tak menghasilkan, lama-lama budaya dan tradisi ini tentu akan ditinggalkan, “ujarnya mengakhiri pembicaraan tentang tenun di NTT.