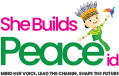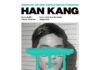Sekolah hanya salah satu bagian, Pendidikan itu juga bisa di rumah, di masyarakat, dan juga di sekolah. Nggak benar kalau pendidikan itu hanya sekolah. Tapi kan masyarakat suka begini ‘orang yang enggak sekolah itu nggak berpendidikan’, itu salah kaprah sebetulnya. – Sri Wahyaningsih.
Wahya memulai pembicaraan topik pendidikan dengan menceritakan kedatangan Romo Mangun suatu waktu ke Sanggar Anak Alam di Lawen. Menurut Wahya, Romo Mangun sempat berkomentar bahwa sekolah semacam itu yang ingin Beliau buat. Rupanya Salam menjadi sumber inspirasi Romo Mangun untuk membentuk sekolah alternatif SD Mangunan di daerah Kalasan, Yogyakarta.
Belajar dari pengalaman menjadi relawan di Bantaran Kali Code, ia merasa bisa mewujudkan Salam di Lawen seperti demikian. Didorong oleh suaminya sebagai sesama aktivis dan pendidik yang kompak, ia menyatakan SALAM ibarat “anak kandung” Romo Mangun juga, sebuah sanggar pendidikan di mana transformasi nilai dan semangatnya lebih “radikal” sebagai pendidikan alternatif.
Kalau Sekolah Eksperimental Mangunan di pinggir kota Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1993 masih memodifikasi kurikulum pemerintah, SALAM bahkan telah mengembangkan kurikulum alternatif sendiri. Namun keduanya merupakan sebagian warisan Romo Mangun, warisan semangat, cita-cita dan gagasan monumental, sejalan dengan cita-cita pendidikan itu sendiri, yaitu memerdekakan.
Hasil dari pendidikan di Lawen memang cukup memberikan optimisme. Dari awal, Salam di Lawen telah mendidik 200an anak usia PAUD sampai SMTA. Ada lulusan yang bisa melanjutkan ke sekolah umum lewat ujian persamaan Paket A, B dan C, bahkan ada yang mencapai sarjana dan bekerja sebagai ASN maupun swasta. Sayang, semangat dalam bidang pendidikan di Lawen, tak memiliki penerus dari warga setempat.
Belakangan kegiatan tersebut sudah bermetamorfosis menjadi kegiatan pemuda dengan nama “Anane 29”. Organisasi tersebut sampai hari ini masih menjadi pelopor untuk kegiatan kemanusiaan di Lawen dan sekitarnya. Para pemuda kini memiliki kesadaran untuk bisa menciptakan lapangan kerja di desa, tidak lagi berurbanisasi.
Sayangnya, sepeninggal Wahya untuk membangun Salam di Yogyakarta, kegiatan belajar anak-anak berangsur-angsur berhenti karena tekanan dari pihak-pihak yang bekerja pada Pemerintah setempat. “Cuma lulusan SD kok mengajar,” begitu komentarnya. Para kader yang sudah terlatih selama belajar bersama Wahya, lama-lama goyah keteguhan hatinya dan kelompok belajar akhirnya berhenti.
Mungkin, karena “Warga di Lawen menjadi makin kritis. Mereka mulai berani memprotes kecurangan dalam pemilihan kepala desa dan berdemonstrasi sampai ke kantor bupati, padahal aparat masih represif,” kisah Wahya. Merasa bangga dengan kesadaran warga, sekaligus juga sedih akan terhentinya sanggar belajar.
Kelak ketika tahun 1996, Wahya dan Toto, suaminya, pindah ke daerah Nitiprayan, Bantul, Yogyakarta, semangat melanjutkan konsep Salam seperti di Lawen terus ada. Apalagi di kampung seni ini, dia dipercaya masyarakat menjadi Ketua RT. Dia mengawalinya dari mengorganisir ibu-ibu. Sebagai ketua RT 04 Kampung Nitiprayan Bantul, Yogyakarta, Wahya mengembangkan Koperasi Karya Aji Nastiti, koperasi simpan pinjam beranggotakan 150 orang, yang 90% nya perempuan.
Wahya juga mengembangkan pelatihan kompos organik yang bekerjasama dengan Yayasan Dian Desa (Yogyakarta). Dengan program ini Wahya menaruh harap, selain peningkatan kualitas kebersihan lingkungan, upaya itu bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Kedekatan dengan warga ini membuat Wahya banyak mengetahui permasalahan di daerah setempat. Ternyata putus sekolah juga menjadi salah satu permasalahan di Nitiprayan.
Wahya dan Toto mulai memetakan pemikiran awal dengan membangun konsep bangunan yang akan mendukung semua kegiatan itu. Ruang depan rumah dibiarkan terbuka dengan bahan bangunan tradisional sehingga cukup bersahabat bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar masih bertani. Letaknya di tengah persawahan, yang hanya bisa diakses melalui jalan setapak seketika mencerminkan bagaimana anak-anak kelak akan melebur dengan suasana di pesawahan.
Ruang depan rumah mereka dimanfaatkan untuk perpustakaan, ruang pertemuan, ruang tamu, sekaligus ruang keluarga. Kelak ketiga anak Wahya pun ikut terlibat aktif di dalam kegiatan sanggar. Selain perpustakaan, Salam juga memberikan pendidikan lingkungan dan pertanian organik untuk anak-anak. Wahya menyewa sebidang tanah di samping rumah untuk depot tanaman organik, di mana anak-anak tak hanya memahami informasi keilmuannya, tapi sekaligus mempraktikkannya.
Rintisan-rintisan yang dilakukan lalu berkembang ke arah kelompok remaja sekitar dengan berbagai kegiatan belajar, seperti jurnalistik, kesenian, fotografi, dan bercocok tanam. Kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Sanggar Anak Alam ke-2 di Nitiprayan, yang terbentuk pada tahun 2000. Meski orang salah kaprah menyebut Salam adalah sekolah alam, sebutan ‘fasilitator’, bukan guru kepada para pendamping anak belajar, mungkin akan seketika bisa membedakannya.
Alasannya filosofi dari Konfusius, yang menjadi dasar pemahaman cara pembelajaran di Salam. Mendengar, Saya Lupa; Melihat, Saya Ingat; Melakukan, Saya Paham; Menemukan Sendiri, Saya Kuasai. Di mana anak didorong untuk mencari dan menemukan sendiri hal yang ingin diketahuinya. Tidak melulu dituntun, diberitahu, disuruh, maupun diajarkan seperti konsep pendidikan mainstream yang banyak diterapkan selama ini.
SALAM mendampingi anak dalam berekspresi melalui sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan terdekatnya, serta memfasilitasi anak bereksplorasi di alam. Anak-anak belajar langsung dari realita yang dekat dengan mereka, belajar dari apa yang mereka sukai. Bagaimana konsep pembelajaran yang berpusat pada riset dari rasa keingintahuan anak, pada akhirnya mampu mendorong anak belajar. Terutama untuk mengamati, mencari tahu kepada sumber yang tepat, menguji coba, memaknai proses termasuk keberhasilan dan kegagalannya, untuk kemudian dituliskan sebagai hasil proses pembelajarannya.
Hal semacam itulah yang diimplementasikan SALAM mulai dari Kelompok Bermain (PAUD) hingga SMA. SALAM, termasuk juga membebaskan anak untuk tidak berseragam ketika pergi ke sekolah, dan senantiasa melakukan elaborasi maupun kolaborasi antar orang tua, antar area tempat tinggal, maupun dengan sumber belajar komunitas, maupun lembaga lain.
Dengan konsep demikian, Wahya, Toto dan tim di Salam selalu menghimbau dan mengajak orang tua untuk berpartisipasi menjadi fasilitator di rumah, atau dengan kata lain, bukan Cuma anak-anak yang menjadi siswa yang belajar, orang tua pun juga turut belajar, sesuai dengan salah satu filosofi Salam : ‘semua orang itu guru, alam raya sekolahku.’
Sampai saat ini, SALAM terus membangun ekosistem pendidikan partisipatif, yang melibatkan lebih dari 600-an orang, terdiri dari siswa, fasilitator dan orang tua. Mengingat konsep pembelajarannya melibatkan semua pihak, konsep tersebut juga tepat dalam membentuk ekosistem belajar yang inklusif.
Di mana orang-orang yang akan berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus tersebut telah lebih dahulu memahami indahnya keberagaman, mengerti bahwa kebutuhan khusus bukan halangan untuk menjalin kerjasama, yang pada akhirnya membuat kolaborasi untuk hal yang lebih baik.
“Dengan ekosistem seperti ini, pada akhirnya seluruh pihak sadar bahwa belajar itu tidak ada habisnya. Anak belajar dari orang tua dan fasilitatornya, orang tua belajar memahami dan menuntun anak serta menerapkan masukan dari fasilitator. Fasilitator belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anak, serta memberi masukan kepada orang tua untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak di rumah,” jelas Bu Wahya tentang situasi dan kondisi proses belajar yang terjadi.
Bila jargon Merdeka Belajar baru diperkenalkan kepada sekolah-sekolah semasa pandemi dua tahun ini oleh Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan terdahulu), Salam Yogyakarta yang Wahya dan Toto ampu malah sudah menjalani dan menghayati dalam konsep pembelajaran sehari-hari. Memahami sebenar-benarnya dengan cara masing-masing siswa ini menjadi panduan pendidikan di Salam Yogya sehingga mampu mengakomodir anak-anak dengan segala keunikan dan kebutuhannya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian di Salam, kerjasama dan saling bahu membahu antara Wahya dan Toto membuka pemikiran banyak orang tentang bagaimana peran perempuan, peran seorang istri dan Ibu. Kapan waktu yang tepat seorang perempuan untuk maju ke depan, kapan sebaiknya memberi dukungan dari belakang saja.
Contoh sederhana, pada masa anak-anak usia PAUD, Wahya banyak mendorong orang tua untuk berupaya ikut dalam setiap proses pembelajaran anak. Konsep ini sungguh memutuskan anggapan bahwa ketika anak sudah bersekolah, tanggung jawab dalam hal pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah saja. Justru orang tua diminta terlibat sepenuhnya, bukan hanya tahu anaknya sedang proses belajar apa, tetapi juga ikut sebagai ‘fasilitator’ di rumah. Ikut belajar, mengamati, sekaligus membuat catatan mengenai perkembangan mereka.
Dari Wahya, para ibu, orang tua maupun fasilitator banyak belajar tentang bagaimana peran perempuan sekaligus peran sebagai Ibu. Bukan sekadar emansipasi dalam arti kesetaraan dengan lelaki, tetapi Wahya mencontohkan bagaimana perempuan bisa seimbang melakukan peran-perannya. Salah satunya tentang asuh didik dalam keluarga.
Seiring usianya yang sudah lebih dari dua dasawarsa, Salam terus belajar dan berdinamika. Bila orang awam melihat Salam sebagai perjalanan batin Wahya dan Toto dalam berproses memaknai pendidikan, tetapi sesungguhnya perjalanan Wahya-lah yang tampak signifikan sejak kecil dan mendewasa.
Frasa We Make Roads By Walking yang ada di salah satu kasus produksi Salam, mungkin tepat untuk menggambarkan praktik sekaligus teori yang dijalani seorang Wahya. Perjalanan Wahya mulai dari tumbuh kembang secara komunal di Klaten, perjuangan bersama masyarakat Code, berpindah ke Sumatera, lalu mewujudkan konsep pendidikan alternatif dengan membangun SALAM di Lawen hingga bersama suaminya Toto Rahardjo di Yogyakarta, semuanya berkelindan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan; berjalan di atas isu kemanusiaan, untuk kehidupan anak-anak Indonesia yang lebih baik.
Ketika diminta apa kesannya menjalani laku hidup yang selalu berkelindan dengan masyarakat kecil dan isu kemanusiaan, Wahya berujar, “Dengan memberi sesungguhnya kita menerima. Hidup saya dipenuhi berkat dan doa dari banyak orang. Ibaratnya di mana-mana sata bisa bertemu saudara. Bukankah itu kekayaan yang sesungguhnya dapat hidup berdampingan dengan damai bersama semua makhluk?”