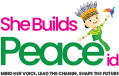Resolusi 1325 PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security) telah berusia lebih dari 20 tahun sejak disahkan pada tanggal 31 Oktober 2000 lalu. Saat ini, 90 negara telah mengadopsi Resolusi 1325 ke dalam rencana- rencana aksi nasional mereka. Dalam resolusi 1325 tersebut semua negara diamanahkan oleh PBB agar dapat mengintegrasikan kesetaraan gender yang substantif dalam membangun perdamaian dan keamanan dalam situasi konflik sosial atau perang.
Memperkuat Resolusi ini, telah ada Rekomendasi Umum 30 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pasca Konflik yang disahkan pada Oktober 2013. Tidak hanya itu, sebagai pelengkap terdapat payung hukum baru, yakni UNDANG-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan dapat membantu para koraban untuk terpenuhi haknya atas penanganan, perlindungan dan pemulihan terutama dalam kepastian pelibatan perempuan dalam penanganan konflik.
Ketiga instrumen tadi diharapkan saling menopang dan menjadi fondasi kuat untuk menjamin kesetaraan gender terintegrasi secara substanstif dalam empat indikator partisipasi perempuan dalam konteks konflik yakni Pencegahan, Partisipasi, Perlindungan, Penyediaan Bantuan dan Pemulihan. Kesemua aspek tadi harus menjadi standar yang diberikan kepada penyintas agar ke depannya, konflik tidak mengorbankan kaum pinggiran dan selanjutnya dapat membantu terwujudnya perdamaian yang lebih membumi dan berkelanjutan.
Terlebih, jika merujuk pengalaman internasional, mayoritas riset menunjukkan bahwa selama ini perempuan terlibat aktif dalam penanganan korban-korban konflik, rekonstruksi pasca konflik, pemulihan serta proses-proses perdamaian maupun melestarikan perdamaian di tengah-tengah komunitasnya. Merujuk laporan data terkait proses kesepakatan damai yang adil gender, terlihat bahwa sejak 1995 partisipasi perempuan meningkat dari 14% menjadi 22% (UN Women, 2019). Perempuan tercatat sebagai negosiator sebanyak 13%, mediator 6% dan peneken 6% dalam proses-proses perdamaian selama rentang waktu 1992-2019.
Pelibatan perempuan dalam peace building atau kesepakatan damai berdampak signifikan untuk melanggengkan perdamaian di tengah-tengah komunitasnya atau masyarakat luas: peningkatan 35% keterlibatan perempuan diperkirakan akan memperpanjang 15 tahun durasi pelaksanaan perjanjian damai. Namun sumbangsih penting perempuan sebagai agen-agen perdamaian yang dijalankan dengan cara-cara khas seturut peran-peran gendernya, cenderung
diabaikan. Dalam meja perundingan khususnya dalam ruang negosiasi dan pengambilan keputusan, perempuan tidak dilibatkan. Juga dalam pemetaan kebutuhan- kebutuhan bantuan komunitas yang terdampak konflik atau perang, pelibatan perempuan dikesampingkan. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak menjawab kebutuhan korban dan komunitas terdampak.
Masalah-masalah tersebut tentunya tidak perlu diulang pada konteks Indonesia setelah UU TPKS disahkan. Sebab, selama ini Komnas Perempuan menyebut bahwa dalam mayoritas konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, perempuan menjadi kelompok paling rentan terdampak dalam perebutan sumber daya di berbagai wilayah. Secara spesifiknya, Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat mengatakan selama 2020-2021 lembaganya menerima sepuluh pengaduan kasus, terdiri dari kasus tambang (dua kasus), hutan adat (dua kasus), serta masing-masing satu kasus polusi
suara/kebisingan dan hak atas air.
Sepanjang 2003-2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan 49 kasus yang semuanya tidak terselesaikan dengan baik. Dalam konteks budaya dan spiritual, perempuan kehilangan perannya sebagai pengelola pengetahuan lokal berbasis sumber daya alam setempat. Perempuan tidak bisa lagi membuat obat-obatan herbal, ritual dan nilai-nilai pertanian masyarakat adat serta kerajinan tangan. Tak hanya itu, ketika kepala keluarga kehilangan hak atas tanah dan sumber daya lainnya, istri dan anak mereka kerap menjadi pelampiasan kekerasan: rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diperdagangkan,
hingga dipekerjakan secara seksual untuk memperoleh uang.
Di luar lingkup keluarga, perempuan juga memiliki risiko tinggi untuk digunakan sebagai alat ancaman pihak keamanan atau preman dengan cara diperkosa atau dinikahi secara paksa. Bahkan dalam momentum konflik, pelaku kekerasan justru dengan lihai memanfaatkan peluang dengan menekan korban agar melayani seksual secara paksa demi memenangkan konflik. Selama ini, banyak dari kasus-kasus tersebut tidak pernah menemukan solusi komprehensif. Bahkan pelakunya kerap terlepas dari jeratan hukum karena relasi kuasa yang amat timpang.
Dengan disahkannya UU TPKS, diharapkan kejadian serupa tidak terulang, meski masih ada celah dalam peraturan ini, sebab di pasal 10 maupun di pasal 60 muatan kontennya rawan dipahami sebagai tindak pidana perdagangan, dan bagi beberapa pihak bisa dimanipulasi untuk lepas dari tindakan hukum. Oleh karenanya, mengndalkan UU TPKS saja tidak cukup, semua pihak termasuk pemerintah perlu memperhatikan persetujuan bebas tanpa tekanan (free, prior and informed consent) untuk setiap proyek pembangunan di atas tanah adat dan juga pembagian keuntungan, dan menyediakan bagi perempuan adat terdampak mata pencaharian alternatif yang layak sejalan dengan Konvensi ILO Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, 1989.