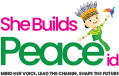Beberapa waktu lalu, saya datang ke Pesantren Ekologi Ath-Thariq di Garut untuk belajar menanam sayur organik. Pulang-pulang, yang saya bawa bukan cuma catatan resep kompos dan jadwal rotasi tanaman, tetapi cara pandang baru.
Merawat tanah adalah cara merawat relasi manusia. Di tangan perempuan, ia bisa menjadi jalan sunyi menuju perdamaian. Di tengah bedengan hijau itu, Nisa Wargadipura menautkan iman, pangan, dan keadilan dengan kalimat terdengar sederhana tetapi bermakna dalam.
“Kalau tanah kita subur, hati kita ikut subur.” Kalimat itu menempel lama, karena terasa seperti inti dari amanah rahmatan lil ‘alamin, ibadah tak berhenti di sajadah, tetapi ia turun ke tanah, air, dan benih. Hablun Minallah, Hablun minannas, dan Hablun minal’alam.
Seringkali kita bicara perdamaian seolah urusannya sekadar ruang negosiasi dan perjanjian di atas kertas. Nyatanya, konflik sering berakar pada perebutan sumber daya, lahan rusak, air mengering, pangan tak terjangkau.
Ketika ekosistem runtuh, sosial pun rapuh. Di Ath-Thariq, saya melihat versi praksis dari agenda Women, Peace, and Security. Agroekologi sebagai strategi damai. Ini bukan semata teknik bertani, ia menggabungkan pengetahuan lokal, keadilan sosial, dan ekologi untuk membangun ketahanan komunitas dari bawah, ketahanan yang mengurangi gesekan karena pangan dan air.
Senada, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ty Sorensen, dkk (2025) yang berjudul “The implications of agroecology for meeting the sustainable development goals (SDGs): a scoping review” menunjukkan, bahwa agroekologi berkontribusi terhadap berbagai target SDGs, dari ketahanan pangan, kesehatan, sampai ekosistem dengan bukti empiris yang makin kuat dalam satu dekade terakhir. Artinya, ini bukan romantisme “kembali ke alam”, melainkan jalan kebijakan yang rasional.
Di banyak komunitas, motor agroekologi justru adalah perempuan. Mereka memilih benih, menjaga tanah, mengatur air, mengolah hasil, sekaligus menenun jaringan dukungan satu sama lain.
Kajian terbaru dilakukan oleh B. Vizuete, dkk (2025) berjudul “More than food production: Assemblages of values underpinning women-led agroecological initiatives”, memaparkan bahwa perempuan petani memimpin inisiatif agroekologi karena nilai kepedulian pada alam, kesehatan, dan keberlanjutan sosial. Nilai-nilai ini juga menumbuhkan kohesi sosial yang sulit dibangun hanya dengan instrumen hukum.
Kohesi itu penting, sebab masyarakat yang saling percaya lebih resilien menghadapi ancaman polarisasi. Saya jadi teringat satu sesi di Ath-Thariq ketika Nisa Wargadipura mengulas tentang benih lokal.
“Benih itu ingatan,” katanya, “di situ ada cuaca, tanah, dan tangan yang merawat.” Dalam ingatan saya, kalimat itu bernuansa politis. Benih adalah hak ingat komunitas, atau hak untuk menentukan apa yang tumbuh di piring, hak atas masa depan yang tidak ditentukan pabrik pupuk dan bibit yang jauh di kota.
Dari hal itu, saya jadi paham mengapa agroekologi yang dipimpin perempuan terasa “menenangkan”. Lebih dari sekadar itu, mengembalikan kontrol dari pasar ke komunitas, dari kompetisi ke gotong royong.
Menariknya lagi, sebuah literatur tentang taman komunitas dan pertanian kota yang dilakukan oleh Kukukaite, dkk (2025) “Improvement of the General Resilience of Social–Ecological Systems on an Urban Scale Through the Strategic Location of Urban Community Gardens”, membahas langsung kaitan antara kebun, resiliensi sosial-ekologis, dan partisipasi warga.
Bila kebun di kota saja mampu mempererat kohesi dan menambah daya lenting menghadapi krisis, apalagi jaringan pesantren, desa, dan kampung yang terhubung oleh pengetahuan agroekologi secara langsung.
Apakah semua ini cukup menghentikan kekerasan? Tentu tidak seketika. Tetapi seperti cara menanam di Ath-Thariq, satu bedengan rapi tidak menyelamatkan panen, namun ia mengajari kedisiplinan, kerja bersama, dan waktu yang sabar. Damai pun begitu, dirawat dari praktek kecil yang konsisten, berbagi benih, musyawarah air, lumbung komunitas, kelas agroekologi untuk santri dan ibu-ibu. Dari praktik kecil yang terasa “biasa”, lahir infrastruktur sosial yang membuat provokasi sulit menyala.
Tugas negara dan masyarakat sipil adalah memperkuatnya, misalnya memberi akses lahan, melindungi pembela lingkungan, dan membuka ruang keputusan untuk perempuan. Dengan begitu, agenda WPS tidak berhenti di dokumen, melainkan tumbuh sebagai pohon yang akarnya memegang tanah, batangnya menahan angin, dan buahnya dapat dinikmati bersama. Karena pada akhirnya, perdamaian yang tahan lama bukan sekadar tiadanya senjata, melainkan hadirnya pangan, air, dan rasa adil yang kita tanam, hari ini, di tanah sendiri.