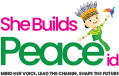Sembari terisak, perempuan paruh baya itu menceritakan kepada jurnalis internasional VOA bagaimana kelompok bersenjata memaksa masuk ke rumahnya dan menodongkan senjata persis di depan wajahnya, “mereka terlihat sangat marah waktu itu. Dengan nada mengancam mereka berkata bahwa suami saya adalah seorang pemberontak. Saya diminta untuk memberitahukan tempat persembunyiannya, atau bila tidak, saya akan dibunuh. Saya juga diminta mereka untuk memberikan senjata milik suami saya. Wallahi.. saya tidak tahu apa-apa. Suami saya pergi begitu saja.”
Meski akhirnya ia selamat, trauma akan perlakuan tersebut masih menghantuinya. Kini, ia hanya bisa berharap konflik di Tigray, wilayah utara Ethiopia ini segera mereda agar ia kembali hidup aman bersama keluarganya. Peperangan di tanah Habsyi sebenarnya bukan hal baru. Sebelum konflik Tigray meletus, tanah Ethiopia punya catatan kelam akibat pertumpahan darah para warga sipilnya akibat perang saudara dengan negara Eritrea selama dua dekade. Sayangnya ketenangan itu tak berlangsung lama.
Ketidakpuasan akan pembagian kekuasaan, hasil pemilihan umum, dan tuntutan reformasi politik usai kesepakatan damai justru mendorong eskalasi konflik baru yang menyebabkan krisis kemanusiaan itu kembali lagi. Konflik ini sendiri bermula saat pemimpin tertinggi Ethiopia Aby Ahmed Ali memerintahkan serangan militer terhadap pasukan regional Tigray yang sebelumnya melakukan agresi ke pangkalan pasukan pemerintah pusat di sana. Bagi pemerintah daerah Tigray, apa yang mereka lakukan hanyalah secuil indikator ketidakpuasan atas banyaknya keputusan Aby yang merugikan Tigray.
Abiy yang seorang liberal membentuk partai baru (Partai Kemakmuran), dan memecat para pemimpin pemerintahan dari Tigray yang dituduh melakukan korupsi dan penindasan. Namun, kebijakan-kebijakan Aby justru dipandang sebelah mata oleh para elit di Tigray. Alih-alih memperoleh sambutan hangat dan apresiasi, pemimpin-pemimpin Tigray memandang reformasi yang dilakukan Abiy sebagai upaya untuk mengambil alih kekuasaan yang mereka miliki dan selanjutnya perlahan-lahan akan menghancurkan sistem federal yang diterapkan di negeri yang terletak di timur Afrika tersebut.
Perselisihan di tingkat elit itu pun makin memanas pada bulan-bulan berikutnya. Akibat dikecewakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) Tigray pun memutuskan untuk menggelar pemilihan umum regional sendiri. Meski di tingkat nasional, pemilu secara serentak dibatalkan penyelenggaraannya akibat pandemi. Melihat sikap memberontak pemdanya, pemerintah pusat lalu menyatakan bahwa pemilu regional Tigray adalah kebijakan illegal dan tidak diakui keabsahannya.
Meski begitu, pemda Tigray tidak bergeming. Mereka bersikukuh menyelenggarakan pesta demokrasi lokal yang kemudian berakibat fatal: pemerintah pusat menangguhkan pendanaan dan memutuskan hubungan dengan Tigray. Keputusan sepihak ini kemudian dianggap oleh Tigray bagaikan menabuh genderang perang. Dan, benar saja, sejak 4 November 2020 lalu Aby memerintahkan pasukan militernya untuk menyerang Tigray yang ia sebut sebagai daerah pembangkang.
Akibat serangan itu, ribuan masyarakat sipil terpaksa mengungsi dan hidup dalam ketakutan. Dampaknya, para perempuan, entah itu istri, saudara, atau anak tentara pemberontak yang tidak turut serta dalam pertempuran, terus menerus dijadikan tumbal peperangan. Rumah mereka didobrak secara paksa oleh tentara yang lalu memerkosa mereka beramai-ramai dengan dalih untuk mengancam para lelaki agar kembali ke rumah dan menyerahkan diri kepada pasukan pemerintah pusat.
Menurut penuturan Mussie Tesfay Atsbaha, salah satu ahli medis di Rumah Sakit Ayder Referral, jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pasukan tentara yang sedang berkonflik sudah mencapai ratusan. Itu pun tidak semua bisa tertangani karena fasilitas yang ada sangatlah terbatas. Belum lagi, banyak dari mereka yang tak berani melaporkan diri atau bahkan meminta bantuan ke pihak medis karena khawatir mereka akan didatangi kembali oleh pelaku dan diperkosa lagi.
Sembari menundukkan kepala Mussie mengatakan bahwa korbannya bukan hanya perempuan dewasa saja. Anak-anak yang tak tahu apa-apa pun ikut diserang. Seorang pasien Mussie berkata bahwa ketika pasukan tentara masuk ke rumahnya, ia secara membabi buta diperkosa dan bayinya ikut dibanting ke lantai. Tangisan si bayi pun tak lantas menghentikan perbuatan kejam itu. Meski si ibu akhirnya selamat, ia mengalami pendarahan hebat yang mengakibatkannya sulit berjalan. Oleh tetangga, ia pun dibawa ke klinik menggunakan kereta yang ditarik oleh keledai.
Hal yang miris, meski sudah jatuh tertimpa tangga, para perempuan korban perkosaan ini masih mengalami stigma negatif oleh beberapa orang di sekitarnya. Kejadian pahit mereka dianggap aib yang perlu ditutup rapat-rapat. Akibatnya, banyak dari mereka yang lebih memilih diam dan menyembunyikan diri. Hal ini membuat sebagian besar korban perkosaan tak tertangani oleh medis, terutama penderita penyakit kelainan seksual akibat perkosaan.
Kondisi mereka dari hari ke hari kini justru kian memburuk. Bantuan kemanusiaan internasional bahkan ditengarai diboikot masuk oleh pemerintah pusat. Warga Tigray terutama kelompok perempuan dan anak mengalami pemiskinan terstruktur yang terus menambah luka fisik dan psikologis.