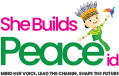“Kelahiran setiap orang itu adalah rahmat. Apapun latar belakang etnis, agama dan kepercayaannya.” — Redy Saputro
Dilahirkan di Bondowoso 32 tahun yang lalu, Redy Saputro menganggap perbedaan adalah keniscayaan. Darah tionghoa mengalir di tubuhnya, mata sipit dan kulit kuning langsat membuatnya mencolok di tengah masyarakat suku Jawa dan Madura. Belum lagi kelompok Kristiani termasuk minoritas di lingkungannya. Ejekan “Cina!”, “Putih!”, “Sipit!” semasa kecil tak lagi asing di telinganya.
Redy kecil tinggal bersama nenek dan tante. Beruntung sekali ia tumbuh dengan ajaran nenek yang melekat sedari dini untuk tidak membeda-bedakan orang dari latar belakangnya. Nilai itu diperkuat dengan menyekolahkan Redy di Taman Kanak-Kanak (TK) umum, dimana mayoritas beragama Islam. Sehingga, Redy meyakini bahwa menjadi etnis Tionghoa dan berkulit terang bukanlah suatu hal yang buruk. “Setiap orang berbeda dan perbedaan itu bukan suatu masalah,” ujarnya.
Bullying yang Redy terima tak membuatnya diam. Ia justru tumbuh menjadi anak yang vokal berbicara, karakter turunan sang ibu. Namun, ejekan yang ia terima justru bertambah, bahkan keluar dari mulut orang tuanya sendiri, “Cerewet!”
Masih terekam jelas dalam ingatan Redy. Ketika mulutnya ditutup dengan plaster, disumpel, dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lainnya yang ia alami semasa kecil, meninggalkan luka dan trauma mendalam. Perceraian kedua orang tuanya pun menjadikan Redy yatim piatu secara sosial. Bullying dan broken home. Luka-luka masa kecil ini berdampak pada proses belajar Redy di sekolah.
Selama duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), ia pernah tak naik kelas hingga dua kali. Bapaknya yang waktu itu mengambil rapot tak sudi lagi ke sekolahnya. “Ini yang terakhir ya!” tegas bapak Redy. Terlintas dalam benak Redy, “Aku bodoh ya?” gejolak pergulatan batin Redy. Namun, lagi lagi ia beruntung dikelilingi perempuan-perempuan hebat, tante Redy membesarkan hatinya, “Nggak papa (tidak naik kelas), yang penting Redy mau sekolah,” kata tante Redy menyemangatinya.
Keberagaman di Lingkar Keluarga
Hidup di keluarga Tionghoa, Redy familiar dengan adat istiadat yang diwariskan turun temurun dan patut dipatuhi oleh tiap generasi. Salah satunya ialah menikah dengan sesama Tionghoa. Namun, tradisi ini mengalami perkembangan zaman. Melihat keberagaman yang ada di Indonesia begitu nyata, keluarga Redy termasuk yang terbuka dengan perbedaan. Keluarga Redy unik. Di keluarga besarnya, beberapa anggota keluarga menikah dengan suku bahkan penganut agama yang berbeda, seperti tantenya yang menikah dengan Muslim keturunan Jawa. Anggota keluarga lainnya menikah dengan orang suku Bali.
Keluarga besar Redy sangat beragam. Ada penganut agama Konghucu, Buddha, Katolik, dan Islam. Di pernikahan keduanya, bapak Redy berpasangan dengan seorang Muslimah. Bahkan, pengasuh Redy saat kecil pun ialah seorang Muslimah. Ibu Arnima namanya. Ia juga termasuk saudara jauh Redy dan telah membantu merawat keluarganya lebih dari 60 tahun sejak 1963 hingga sekarang. Bu Arnima sering mengantarkan Redy dan adiknya sewaktu kecil ke gereja dan menunggu mereka hingga selesai beribadah.
Redy tidak asing dengan kelompok berbeda sejak kecil. Selain dari keragaman anggota keluarga, ia juga sering mengikuti orang tua dan kakek neneknya berdagang di pasar. Karakter yang humble dan aktif berbicara memudahkan Redy untuk berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Ia akrab dengan anak penjaga toko di pasar yang beragama Muslim. Orang tuanya pun mempekerjakan pegawai untuk menjaga toko beragama Muslim. Sejak kecil, Redy begitu dekat dengan keberagaman.
Menjadi Aktivis di Usia Dini
Beranjak remaja, Redy aktif berorganisasi di sekolah. Ia terlibat dalam kepengurusan OSIS SMP menjadi Seksi Daya Kreasi. Ia juga pernah menjadi pemimpin redaksi Mading Indra Prastha (Madita). Ia bersama timnya bahkan pernah menyabet juara II lomba mading bertemakan Flu Burung se-kabupaten Bondowoso di tahun 2009.
Saat waktu senggang, Redy selalu mengisi kekosongan dengan kegiatan positif seperti berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan ia juga seringkali eksplor berkeliling tanah kelahirannya. Sampai suatu ketika, ia berkunjung ke Pusat Informasi Megalitikum yang bertempat di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.
Salah satu kabupaten di Jawa Timur ini memiliki lebih dari 1.000 benda-benda peninggalan zaman batu seperti sarkofagus, kubur bilik, menhir, dolmen, dan batu dakon. Ribuan benda peninggalan zaman batu tersebar di berbagai situs di Bondowoso. Hal ini tentu menjadi daya tarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Termasuk di sekitar rumah Redy, terdapat 58 peninggalan pra sejarah zaman batu. Saat duduk di bangku SMP, ia mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda zaman megalitikum di sekolahnya. Namun, Redy merasa pengetahuan yang ia terima di kelas hanya sebatas verbal saja tidak cukup. Ia justru ingin mempelajari lebih dalam tentang benda-benda peninggalan zaman batu tersebut.
Keresahan ini membawa Redy di usia 15 tahun yang masih mengenakan seragam putih-biru, membentuk sebuah wadah untuk meningkatkan rasa kepemilikan warga lokal terhadap peninggalan sejarah dan mempromosikan kekayaan alam, budaya dan sejarah Bondowoso bernama Komunitas Pemuda Pelopor Pariwisata Budaya (KP3B) pada 10 November 2007. Kegiatan KP3B ialah jelajah budaya dan studi lapangan langsung ke Pusat Informasi Megalitikum di Bondowoso. Upaya-upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal tentu bagian dari mewujudkan perdamaian. Suatu masyarakat yang tercerabut dari nilai-nilai budayanya akan lebih rentan terjangkit virus ekstremisme kekerasan. Dari inisiasi yang digagas Redy, sudah muncul benih-benih peacebuilder. Kini, upaya-upaya pelestarian budaya, tradisi dan kearifan lokal masih tetap ada. Meski KP3B saat ini telah bertransformasi menjadi Bondowoso Tempoe Doeloe.
*Bersambung