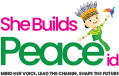“Memang di Pangkep ini ada program teman-teman Kapal Perempuan yang mana dia punya Sekolah Perempuan. Tetapi hanya di pulau yang dekat, yang perjalanan hanya 15 menit, 30 menit itu sudah tiba. Saya kemudian berpikir bagaimana dengan teman-teman, ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang pulaunya terjauh ini? Nah, makanya saya bilang yang dekat ini banyak yang mengerjakan. Bagaimana dengan pulau yang jauh itu tidak ada yang mengerjakan”
Kira-kira begitu jawaban Haniah ketika ditanya mengapa mempunyai inisiatif melakukan pendampingan desa di wilayah terluar Kabupaten Pangkep (Panjakene dan Kepulauan), Sulawesi Selatan, selama lima tahun terakhir. Dari sekian banyak pulau terbentang di wilayah kabupaten Pangkep, Haniah memilih pulau-pulau terluar dengan akses yang sulit dijangkau.
Kehidupan masyarakat di pulau-pulau tersebut pun serba terbatas. Haniah bercerita, masyarakat di sana harus memiliki genset agar dapat menikmati listrik yang beroperasi hanya di waktu-waktu tertentu. Sebagian wilayah malah tidak dialiri listrik sama sekali. Karena aksesnya yang jauh, harga kebutuhan pokok masyarakat juga sangat mahal. Hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya. Belum lagi terkait akses pendidikan yang sulit. Alhasil kemiskinan dan pendidikan menjadi problem utama sekaligus menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak yang berujung pada masalah-masalah lain yang berkelindan di dalamnya.
Melihat kerentanan dan juga kesulitan pada masyarakat pulau itulah yang kemudian membuat Haniah tergugah. Bertahun-tahun terjun menjadi pekerja sosial membuatnya tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan. Haniah pun memutuskan untuk membentuk resiliensi dalam masyarakat, setidaknya merubah mindset masyarakat pulau supaya lebih maju dan lebih mandiri melalui pemberdayaan perempuan dan anak.
Haniah dan Dunia Aktivisme: Mendobrak Kebiasaan Budaya Makassar
Keluar dari zona nyaman sepertinya memang sudah menjadi kebiasaan dan karakteristik Haniah. Pasalnya, sejak belia Haniah dikenal dengan penampilannya yang tomboy dan tidak bisa diam. Perempuan kelahiran Makassar 7 November 1975 ini dibesarkan dalam keluarga dengan latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan budaya Makassar yang sangat patriarki. Perempuan masih dianggap sebagai makhluk domestik yang hanya menjadi istri dan ibu saja. Tak heran kakak-kakak perempuannya kebanyakan menikah di usia anak dan pendidikannya hanya sampai SMP.
Namun, menjadi anak ke 11 dari 12 bersaudara nampaknya memberikan berkah tersendiri bagi Haniah. Dia bercerita bahwa dari kakak pertama sampai yang ketujuh tidak melanjutkan sekolah karena budaya patriarki tadi. Nasib baik, saudara urutan setelahnya melanjutkan sekolah, termasuk Haniah. Kondisi tersebutlah yang membuat Haniah dapat melakukan perbandingan dan meyakinkan orang tuanya agar memberikannya kepercayaan untuk beraktivitas lebih banyak di luar rumah. Perubahan zaman dan banyaknya cerita reflektif yang diterima orang tuanya akhirnya mampu meyakinkan mereka untuk memberikan kepercayaan kepada putrinya.
Pembawaan yang energik dan tidak bisa diam mengantarkan Haniah pada dunia aktivisme sejak di bangku kuliah. Ia sudah dikenal sebagai aktivis sejak masih berstatus mahasiswi Fakultas Ushuluddin Program Studi Perbandingan Agama IAIN Alauddin Makassar. Dia bercerita bahwa sedari dahulu dia sudah tertarik untuk menyuarakan ketidakadilan di tengah minimnya teman-teman perempuan yang mau turun aksi. Kala itu dia mengkritik “Ngapain kita tonton para lelaki aksi dan orasi, saya perempuan mau juga orasi”. Saking asyiknya bergelut di dunia aktivisme mahasiswa, Haniah bercerita bahwa dia sampai molor lulus kuliah hingga tujuh tahun demi menjaga nilainya agar tidak anjlok.
Aktivitasnya itulah yang membuatnya jarang ada di rumah. Menurutnya, anak perempuan yang jarang ada di rumah dan tidak dicari orang tua untuk ukuran masyarakat Makassar merupakan hal yang tergolong luar biasa. Artinya, Haniah keluar dari kebiasaan dan adat budaya Makassar yang masih cenderung patriarki. Walaupun orang tuanya cenderung mengizinkan aktivitasnya, namun tidak jarang Haniah tetap ditegur dan dimarahi orang tua karena kentalnya budaya patriarki tersebut. Namun Haniah tetap di jalannya, lempeng dan cuek sebagaimana pembawaannya.
Tahun 2000 adalah tahun titik balik kehidupannya. Ketika itu dia diajak almarhum Sora Andi Baso untuk menjadi staff pendamping lapangan di Yayasan Lembaga Konsumen (YLK). Pada saat itu Haniah dikirim ke lapangan untuk melakukan pelatihan dan Pendidikan terkait Pendidikan kritis konsumen. Tiga bulan di YLK, Haniah kemudian diutus untuk mengikuti kursus pola pengorganisasian oleh Indonesian Society for Social Transformation (INSIST) yang ada di Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut Haniah menemukan banyak teori dan insight baru tentang pola-pola pengorganisasian masyarakat. Di situlah kemudian Haniah semakin tertarik pada dunia gerakan aktivisme dan memutuskan untuk terus berada di jalan pergerakan kemanusiaan.
Keputusan tersebut membuat Haniah selalu terlibat aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan. Pasca Tsunami Aceh, Haniah terlibat sebagai Programme Officer Anti Trafficking terhadap perempuan dan anak dari bulan September 2005 hingga Januari 2006. Lalu ia melanjutkan partisipasinya sebagai staff Programme Officer Koalisi Perempuan Indonesia di Nanggroe Aceh Darussalam pada Februari 2006 hingga Januari 2007.
Tak berhenti sampai di situ, Haniah juga aktif sebagai anggota Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel, Presidium Kelompok Kepentingan Pemuda, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sulsel, Divisi Perempuan dan Lingkungan Solidaritas Perempuan (SP) Angin Mamiri, aktif di berbagai pelatihan dan advokasi, dan masih banyak lagi. Artinya, pengalamannya dalam bidang kefasilitatoran dan pendampingan perempuan sudah tidak diragukan lagi.
Membaca Kerentanan Masyarakat di Pulau Terluar: Dari Akses yang Terbatas Hingga Perkawinan Anak.
Critical Thinking dan kepekaan Haniah yang terus terasah selama bertahun-tahun menjadi pekerja sosial, membuatnya tergugah untuk melihat kerentanan masyarakat pulau dan melakukan pendampingan di wilayah tersebut. Pulau yang dimaksud adalah pulau terluar seperti pulau Sapoka, Tanaya, Dewaka, Dual-dual Lampo, dan Mattiro Matae yang mempunyai akses paling jauh dari kota Makassar. Haniah bercerita paling jauh bisa sampai 18 jam dari pusat kota.
Karena lokasi yang sangat jauh dari pusat kota, ditambah transportasi yang kurang memadai, masyarakat menjadi kesulitan mengakses informasi. Akibatnya, masyarakat menelan mentah-mentah informasi yang tidak benar. Letak pulau yang justru lebih dekat dengan Lombok dan Kalimantan membuat masyarakat rentan mendapat informasi hoax dan pengaruh dari luar kabupaten tersebut. Saat ini bahkan Haniah menemukan ada beberapa pelajar yang menggunakan komix (obat batuk) sebagai pengganti Sabu/narkoba. Kasus tersebut menunjukkan kenakalan remaja yang diakibatkan oleh minimnya informasi yang bermanfaat untuk mereka.
“Masyarakat pulau yang jauh ini sangat rentan, Kita juga tidak bisa melihat kasus-kasus kekerasan di sana kalau kita tidak kesana langsung. Padahal di sana angka perkawinan anak dan angka perceraian cukup tinggi. Banyak istri yang ditinggal pergi suami merantau dan tidak kembali lagi itu banyak,” lanjutnya
Terkait Pendidikan, Haniah merasa prihatin karena background Pendidikan masyarakat di sana rata-rata hanya sampai SD. Sehingga mereka rentan mengalami diskriminasi dari pihak yang lebih berkuasa, dalam hal ini punggawa. Mayoritas penduduk yang bekerja sebagai nelayan tidak bisa menentukan harga hasil tangkapan ikannya, punggawa lah yang menentukan. Ini memberikan pengaruh pada kesejahteraan nelayan dan mayoritas penduduk di situ.
“Jadi semisal saya nelayan dan ngutang untuk beli BBM ketika mau melaut. Saya ngutang sama nene sebagai punggawa karena dia yang punya banyak uang, nah ketika saya pulang dapat ikan, ikan harus saya jual ke nene karena dia yang punya uang, harga pun ditentukan oleh nene,” ujarnya.
Kesejahteraan nelayan yang kurang berbanding lurus dengan tingginya angka perkawinan anak. Karena kemiskinan dan untuk mengurangi beban keluarga, kemudian anak perempuan dinikahkan di bawah umur sebagai pengalihan tanggung jawab kepada suami. Karena perkawinan dilakukan saat anak di bawah umur yang notabene belum siap secara fisik maupun mental, maka tingkat perceraian dan angka kematian ibu melahirkan juga tinggi.
Ditambah lagi, belum banyak aktivis yang terjun langsung melakukan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar tersebut. Padahal kebutuhan mereka akan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sangat urgen. Inilah kemudian yang mendorong Haniah keluar dari zona nyaman, meninggalkan fasilitas yang nyaman di darat dan ke sana kemari dari pulau ke pulau melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan anak.
Ketika ditanya apakah ada kerentanan terkait ekstremisme kekerasan karena mereka terletak di wilayah perbatasan, Haniah menjawab bahwa sampai saat ini belum terlihat adanya kerentanan tersebut. Memang, masyarakat Sulawesi agak sensitif dengan isu-isu berbau kesukuan, namun di wilayah dampingannya, antara mayoritas dan minoritas terjalin relasi yang rukun, tidak ada pihak yang mendominasi dan didominasi antara mayoritas dan minoritas.