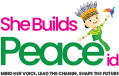Usai mengalami pergolakan sosial politik akibat perang lebih dari tujuh tahun lamanya, hingga kini kondisi di Irak belum sepenuhnya stabil. Terlebih, lanskap sosial dan politik Irak telah berubah secara drastis setelah meningkatnya persaingan kekuatan regional dan global, hingga krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, serta pemberontakan yang belum ditangani dengan baik.
Tak hanya itu, pada Oktober 2019 lalu mayoritas warga mengadakan demo damai yang mengarah pada tuntutan pembentukan pemerintahan baru. Perkembangan ini kian memperburuk ketegangan yang sudah berlangsung lama, memicu ketidakpercayaan publik terhadap negara dan kekerasan suku di selatan. Bahkan efek dominonya berdampak buruk bagi komunitas minoritas, terutama di daerah yang masih bergulat dengan serangan ISIS, menciptakan celah bagi ISIS untuk sewaktu-waktu memborbardir wilayah yang masih menjadi sengketa.
Walau akhirnya terbentuk juga pemerintahan baru pada Mei 2020 yang mengakhiri kebuntuan politik selama berbulan-bulan, tetapi tekanan fiskal, persaingan politik, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas menghadirkan rintangan serius bagi reformasi—seperti bagaimana memperkuat pemerintahan dan mengatasi korupsi. Jika semua dapat dikendalikan dengan baik, tentu ini akan berpengaruh pada stabilitas jangka panjang di Irak dan di lingkup regional.
Sedikit angin segar terkait kondisi sosial politik tadi memang melegakan, namun isu perempuan di Irak sepertinya masih banyak yang belum tersentuh meski perempuan mewakili setengah dari populasi di sana. Posisi mereka hampir tidak terlihat di ruang publik. Dalam masyarakat ultra-konservatif tersebut, banyak hak dan kebutuhan mereka tak terakomodasi. Fakta ini terefleksi dari tingkat buta huruf di kalangan remaja putrid yang mencapai dua kali lipat dari laki-laki.
Sementara itu, hanya 14 persen perempuan yang berpenghasilan, jauh tertinggal dibandingkan dengan 73 persen laki-laki. Dan, ketika sekitar 85 persen wanita berusia 15 tahun ke atas, tidak berpartisipasi pada angkatan kerja Irak, mereka memiliki risiko yang lebih tinggi untuk jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan — meskipun mereka mungkin mengambil bagian dalam ekonomi informal dengan melakukan pekerjaan seperti menjahit atau kerajinan tangan, namun aktivitas tersebut tidak memberikan balas jasa yang memadai.
Mirisnya, jika mereka bisa memperoleh pekerjaan formal, mereka menghadapi risiko pelecehan dan intimidasi di tempat kerja. Di saat yang sama, para perempuan pekerja di Irak masih tidak menerima gaji yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Padahal, perempuan kepala rumah tangga perbadingannya 1 dari 10, dan sekitar 80 persen dari populasi kelompok tersebut berstatus sebagai janda.
Situasi ini pun memunculkan sekelompok perempuan yang akhirnya tergerak untuk mendorong perubahan, salah satunya adalah Ala Ali. Selama tujuh belas tahun terakhir, Ala telah mengabdikan dirinya untuk mempromosikan demokrasi dan terus menerus mengupayakan perdamaian, serta menyuarakan kebutuhan perempuan di daerah post- konflik.
Ala sendiri banyak aktif di Wilayah Kurdistan, dan memiliki pengalaman substansial dalam mengelola dan mengelola program yang didanai oleh badan-badan PBB dan donor internasional lainnya. Ala adalah spesialis dalam studi analisis konflik, strategi pembangunan perdamaian dan demokrasi organisasi. Dia telah menjadi anggota Asosiasi al-Amal Irak sejak 1995, dan terpilih menjadi dewan pengawas pada 2008 dan 2012.
Selain pekerjaannya sebagai konsultan nasional di Program Pembangunan PBB- Irak, Ala pernah menjabat sebagai Program Irak Koordinator dengan Olof Palme International Center, Senior Regional Program Officer dengan International Foundation for Electoral Systems (IFES), Konsultan Peacebuilding dengan UN Development Program, dan Country Manager of Women in Technology dengan Institute of International Education.
Ala meraih gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Sipil dan MBA dan Master of Arts dalam Transformasi Konflik dari Eastern Mennonite University- Center for Justice and Peace, Virginia-USA. Di samping aktivismenya tadi, sebagian besar pekerjaan Ala berfokus pada studi akar kekerasan di provinsi Anbar yang bergolak di Irak, di luar ISIS. Pada Desember 2013, setelah konflik Irak sempat mereda, Ala menjelaskan bahwa mereka sempat mengalami gonjang ganjing kembali karena pasukan keamanan nasional Irak menyerbu kediaman pribadi Menteri Keuangan Irak, menuduh beberapa stafnya mendukung terorisme.
Tak pelak, insiden ini memicu permusuhan lama di provinsi tersebut. Singkat kata, “Sunni menuduh Maliki mengikuti agenda pemerintah Iran dan sebaliknya, Maliki dan pengikutnya menuduh blok Sunni mengikuti agenda Arab Saudi dan Qatar,” begitu penjelasan Ala. Lebih lanjut, ia menyayangkan bahwa agama, suku, nasionalisme, dan kesukuan masing-masing digunakan sebagai alat politik untuk memobilisasi satu kelompok melawan yang lain.
Setelah beberapa dekade kediktatoran, Ala juga masih kesulitan untuk menjembatani musyawarah mufakat untuk meredakan konflik. Di Irak, budaya dialog masih belum ada dan konsep identitas nasional masih sulit dipahami. Ala berharap ke depannya pemerintah Irak, kelompok-kelompok yang bertikai baik dari komunitas agama maupun pihak pemberontak, hingga berbagai komunitas internasional mau turun gunung untuk berdialog dan menyepakati persatuan. Sebab, jika tidak segera direalisasikan situasi perdamaian sepertinya masih sebatas harapan.