Di kampungku Kalisidi, Ungaran Barat, Jawa Tengah, tidak ada yang menyangkal jika bulan Suro atau Muharram adalah bulan yang mistis. Banyak pantangan yang tidak boleh dilakukan pada bulan Suro, dan yang paling populer adalah pantangan mengadakan pesta atau hajatan. Karena dianggap bulan berbahaya, maka tradisi ritual Suronan selalu diadakan setiap tahunnya.
Suronan menjadi ruang perjumpaan masyarakat untuk mengeratkan relasi antar warga dalam budaya kebersamaan sembari menjaga tradisi kampung yang sudah ada sejak dahulu. Suronan dimulai dengan membaca doa akhir tahun pada malam 1 Suro, dilanjutkan dengan selametan, dan diakhiri dengan ziarah kubur yang diikuti oleh seluruh warga kampung. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa tradisi Suronan, sejatinya tetap ada hingga hari ini karena para perempuan lah yang menjaga dan melestarikan tradisi itu.
Simbol Kohesi Sosial pada Tradisi Lokal
Suronan selalu identik dengan hidangan makanan khas yang tidak setiap waktu ada seperti, bubur Suro, apem, bubur merah putih, nasi tumpeng, dan ayam ingkung. Adanya beragam hidangan dalam ruang perjumpaan melengkapi momen kebersamaan, dan para perempuanlah yang berdiri di garis terdepan.
Karakter khas perempuan yang dekat dengan narasi kehidupan karena ia memiliki rahim, sehingga peran perempuan cenderung menjaga dan melindungi. Memastikan Suronan yang berjalan dengan lancar adalah salah satu bukti perempuan turut berperan aktif dalam menjaga dan melindungi tradisi turun temurun yang ada di kampungnya.
Menariknya, di kampungku laki-laki dan perempuan saling berbagi peran. Di saat para perempuan menyiapkan makanan khas Suronan, maka laki-laki bertugas untuk membersihkan sumber air, saluran irigasi makam tempat berziarah, dan lingkungan sekitar kampung. Secara alami, Suronan menjadi ruang perjumpaan yang berdampak pada kohesi sosial yang kuat di masyarakat kampungku.
Menjelang tradisi Suronan, masyarakat kampungku selalu mengawalinya dengan rapat yang melibatkan pengurus kampung baik laki-laki maupun perempuan. Para laki-laki dilibatkan dalam hal-hal terkait pembersihan mata air, saluran irigasi, makam hingga lingkungan sekitar kampung. Sedangkan para perempuan dilibatkan dalam pembuatan anggaran yang nantinya akan digunakan untuk memasak makanan khas tradisi Suronan dan memastikan bahwa makanan khas Suronan dapat dihadirkan tepat pada waktunya.
Sore hari setelah hidangan siap, bapak-bapak mulai menggelar tikar di sepanjang jalan kampung. Mereka meletakkan daun pisang dan menyusunnya sepanjang tikar yang ada. Setelah itu, ibu-ibu akan bergantian menata makanan yang mereka bawa di atas daun pisang untuk nantinya dinikmati bersama.
Doa bersama dalam rangka Suronan dipimpin oleh Kyai kampungku. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, berbaur dengan duduk berderet di atas tikar yang sudah digelar sebelumnya. Semua warga yang hadir nampak khusyuk mengaminkan doa keselamatan. Saat doa selesai dibaca, para perempuan bergegas membagikan makanan kepada warga yang hadir di sana.
Makanan khas Suronan sudah siap, jalanan kampung rapi, sumber air, saluran irigasi, dan makam juga sudah bersih. Ritual tradisi Suronan di kampungku terasa sangat mendamaikan. Hal ini tidak lepas dari kebersamaan laki-laki dan perempuan di kampungku yang saling berbagi peran dalam menyukseskan tradisi Suronan.
Selepas doa bersama dan selametan di malam harinya, tradisi Suronan dilanjut dengan ziarah keesokan harinya. Masyarakat wajib membawa air wangi dan bunga tabur saat melakukan ziarah kubur Suronan. Seluruh masyarakat mendoakan para leluhur dan memanjatkan doa keselamatan untuk kehidupan yang damai dan sejahtera.
Menentang Ibuisme dalam Praktik Budaya
Kendati dalam tradisi Suronan baik perempuan dan laki-laki terlihat saling merawat budaya lokal, tetapi di kampungku masih ditemukan bias ideologi ibuisme. Ideologi warisan pemerintahan Orde Baru yang diciptakan oleh Negara sebagai dasar untuk mengatur dan membentuk sosok perempuan ideal menurut Negara.
Menurut Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis dalam esainya yang bertajuk “Ibuism and Priyayisation” (1987), Ibuisme adalah sebuah ideologi yang memposisikan kaum perempuan untuk mengurus keluarga, kelompok, kelas, atau negaranya dengan tanpa menuntut pamrih berupa privilese (keistimewaan) dan kekuasaan sebagai imbalan. Sebagaimana ditulis oleh
Praktik dari ideologi ibuisme di kampungku sangat ketara seperti perempuan bertugas memasak makanan khas Suronan, menyiapkan air wangi dan bunga tabur untuk ziarah kubur, hingga mengasuh anak di rumah selama para bapakkhusyuk mengikuti rentetan ritual Suronan di kampung.
Semua tugas itu telah dilakukan sejak nenek moyang kami. Tidak heran, budaya patriarkis masih menguat kala itu. Namun, aku rasa saat ini suara perempuan sudah mulai diperhitungkan.
Bukankah akan lebih indah jika laki-laki juga berperan dalam hal domestik seperti memasak, menjaga anak, dan menyiapkan peralatan tradisi? Begitupun perempuan misalnya memimpin doa keselamatan dan kesejahteraan. Berharap imajinasi itu tidak hanya di kepala saja, tetapi terejawantahkan dalam kehidupan. Semoga.

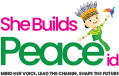

![13200830_603df0ae76cfe0182de9da7f [Converted]](https://shebuildspeace.id/wp-content/uploads/2025/07/13200830_603df0ae76cfe0182de9da7f-Converted-1068x580.jpg)




