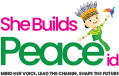Raden Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai perintis pendidikan bagi kaum wanita. Ia lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Kabupaten Bandung, dari keluarga bangsawan Sunda. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat besar terhadap dunia pendidikan.
Dalam permainan masa kecilnya, Dewi Sartika sering berperan sebagai guru yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung kepada teman-temannya. Kebiasaan ini menjadi awal dari tekadnya untuk memajukan pendidikan perempuan di Indonesia.
Kehidupan Masa Kecil Dewi Sartika
Masa kecil Dewi Sartika tidak selalu berjalan baik. Ayahnya pernah mengalami peristiwa pahit yang membuat keluarga mereka kehilangan sebagian besar harta benda. Kondisi ini memaksa Dewi Sartika tinggal bersama pamannya, seorang Patih di Bandung, yang tetap memberikan kesempatan baginya untuk belajar.
Dari lingkungan inilah ia mengenal berbagai cara mengajar, termasuk metode yang digunakan di sekolah Belanda. Ia mulai mengajarkan keterampilan dasar kepada anak-anak di sekitar rumahnya, meski hanya menggunakan alat sederhana seperti batu tulis.
Dorongan untuk memajukan pendidikan perempuan semakin kuat setelah Dewi Sartika melihat terbatasnya akses belajar bagi kelompok perempuan pada masa itu. Ia menyadari bahwa banyak perempuan hanya mendapatkan pengetahuan seputar pekerjaan rumah tangga tanpa kesempatan mengembangkan potensi diri. Melalui bekal pendidikan, pengalaman, dan dukungan keluarga, ia bertekad membuka peluang belajar yang lebih luas bagi perempuan, terutama di bumi Sunda.
Sakola Kautamaan Isteri: Affirmative Action
Sakola Kautamaan Isteri yang didirikan Dewi Sartika pada 16 Januari 1904 di Bandung menjadi langkah besar dan Affirmative Action dalam memperjuangkan pendidikan perempuan di Indonesia.
Saat itu, kesempatan belajar bagi perempuan sangat terbatas. Sebagian besar hanya diajarkan keterampilan mengurus rumah, sementara akses pada pengetahuan umum jarang diberikan. Melihat kenyataan tersebut, Dewi Sartika ingin menghadirkan tempat belajar yang memberikan bekal ilmu sekaligus keterampilan praktis.
Di sekolah tersebut, murid-murid perempuan belajar membaca, menulis, berhitung, menjahit, memasak, dan mengatur keuangan rumah tangga. Semua pelajaran tersebut diharapkan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri dan mampu berperan aktif di masyarakat.
Keberadaan Sakola Kautamaan Isteri mendapat sambutan hangat dari masyarakat Bandung. Banyak orang tua mulai melihat pentingnya pendidikan untuk anak perempuan. Murid-murid yang belajar di sekolah tersebut menunjukkan perubahan cara berpikir dan memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.
Berkat dukungan dari warga dan perhatian pemerintah Hindia Belanda, Sakola Kautamaan Isteri berkembang pesat. Dalam beberapa tahun saja, jumlah murid bertambah dan cabang sekolah dibuka di berbagai kota di Jawa Barat. Kehadiran Sakola Kautamaan Isteri mendorong munculnya kesadaran perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Model pendidikan yang diterapkan di Sakola Kautamaan Isteri mulai diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1910, sekolah ini telah dikenal luas sebagai contoh keberhasilan pendidikan perempuan.
Kegiatan belajar yang memadukan pengetahuan umum dan keterampilan rumah tangga dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Hasilnya, pendidikan mampu membuka peluang baru bagi perempuan untuk ikut berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di ranah publik, tidak terkungkung pada pekerjaan domestik.
Pemikiran Dewi Sartika tentang Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan
Pemikiran Dewi Sartika mengenai pendidikan perempuan berangkat dari kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan terbukanya akses terhadap ilmu pengetahuan. Ia meyakini bahwa kemampuan literasi, keterampilan praktis, dan pemahaman agama yang benar akan mengangkat derajat perempuan serta meningkatkan kontribusinya dalam kehidupan sosial.
Konsep tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang memandang bahwa menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi seluruh umat manusia. Latar belakang sosial dan budaya masa kolonial memberikan pengaruh signifikan terhadap gagasan Dewi Sartika.
Ia menyaksikan secara langsung kondisi perempuan yang terkungkung oleh budaya patriarkis, tidak memiliki akses pendidikan, serta rentan terhadap praktik sosial yang merugikan. Pengalaman tersebut melahirkan tekad untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan umum dan pendidikan agama.
Saya melihat bahwa Dewi Sartika berharap sekolah yang ia dirikan mampu melahirkan perempuan yang mandiri, berpengetahuan luas, dan memahami hak serta kewajiban dalam kerangka ajaran Islam yang berkeadilan.
Dewi Sartika juga memberikan perhatian terhadap praktik sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Ia menolak praktik kawin paksa, kawin gantung, perceraian sepihak, dan poligami yang tidak memenuhi ketentuan syariat.
Pandangan tersebut secara tidak langsung menyoroti perjuangan pendidikan yang ia lakukan tidak terlepas dari upaya pembaruan sosial. Ia memandang perbaikan kedudukan perempuan harus disertai dengan pemahaman yang benar terhadap ajaran agama, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang harmonis.
Gagasan Dewi Sartika secara substansial tercermin dalam karya tulisnya dalam Bahasa Belanda berjudul De Inlandsche Vrouw, artinya “Perempuan Pribumi”. Pada tulisannya tersebut, ia menegaskan pentingnya pendidikan untuk membentuk perempuan yang sehat jasmani, kuat rohani, dan berbudi pekerti luhur.
Bukan sekedar tulisan, melainkan aksi nyata. Melalui Sakola Keutamaan Isteri, Dewi Sartika mengupayakan terwujudnya perempuanan-perempuan yang mampu berdaya secara intelektual dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Referensi:
Museum Pendidikan Nasional UPI (2021). Sejarah Sakola Istri – Museum Pendidikan Nasional. [online] Museum Pendidikan Nasional. Available at: https://museumpendidikannasional.upi.edu/sejarah-sakola-istri/ [Accessed 15 Aug. 2025].
Faujiah (2020). PEMIKIRAN DEWI SARTIKA PADA TAHUN 1904-1947 DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 17(02), pp.205–212. doi:https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v17i2.10402.