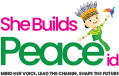Ketika bicara soal tokoh pahlawan atau pejuang perempuan, mungkin hampir semua orang langsung teringat pada nama R.A. Kartini. Sosok perempuan pejuang emansipasi yang surat-suratnya menggugah, dan perjuangannya membuka akses pendidikan bagi perempuan Indonesia.
Dibalik sorotan yang terang itu, ada banyak tokoh perempuan lain yang juga mewarnai sejarah Indonesia dengan keberanian dan keteguhan hati mereka, meski tak selalu mendapat tempat dalam buku pelajaran atau panggung peringatan nasional. Salah satunya adalah Maria Walanda Maramis.
Saat pertama kali membaca tentang Maria Walanda Maramis, aku merasakan hal yang luar biasa. Bukan sekadar karena namanya terdengar seperti orang dari buku sejarah klasik, melainkan karena gagasan yang dia tanam sejak berusia muda bahwa perempuan layak lebih dari sekadar duduk di dapur.
Maria lahir pada 1 Desember 1872 di Kema, Minahasa. Ia harus kehilangan orang tua saat baru berusia enam tahun. Meskipun akses pendidikannya sangat terbatas, hanya sampai sekolah melayu dasar selama tiga tahun.
Sekolah ini adalah sekolah formal untuk anak-anak bumiputra pada masa kolonial, dengan kurikulum dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Bagi perempuan, sekolah ini satu-satunya akses pendidikan formal yang tersedia.
Meskipun begitu, semangat belajar Maria tidak pernah berhenti. Ia terus belajar. Salah satunya melalui interaksi dengan pendeta Belanda dan lingkungan terpelajar, yang membuat pandangannya mulai terbuka tentang kemajuan dan pendidikan perempuan, jauh melampaui batasan adat zaman itu.
Pada 8 Juli 1917, dia mendirikan organisasi PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya). Awalnya kegiatan ini seperti dialog antar ibu. Tentang memasak, merajut, pola asuh anak, tapi kemudian berkembang menjadi ruang diskusi kritis, wadah pendidikan bagi perempuan pribumi sungguhan. Hingga cabang-cabang PIKAT muncul di Sulawesi, bahkan menyebar ke Jawa hingga Surabaya dan Bogor.
Ia membuka “huishoudschool” atau sekolah rumah tangga pada 1918, kemudian sekolah kejuruan perempuan pada 1932. Semua itu bukan sekadar soal keterampilan domestik, tetapi soal menyiapkan perempuan untuk hadir dalam ruang publik, berpikir kritis, dan menyuarakan haknya. Bahkan ia menulis artikel di koran lokal Tjahaja Siang, mendesak pentingnya pendidikan kesehatan, pengasuhan, dan kesetaraan suara politik bagi perempuan.
Di era di mana perempuan dianggap tidak perlu bersuara dalam pemilihan umum, Maria memprotes keras. Ia menulis surat protes ke pemerintahan kolonial di Batavia agar perempuan diizinkan memilih dalam pemilu Minahasa Raad. Tender risalahnya tidak sia-sia. Pada 1912, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memberi peluang perempuan memberikan suara dan bahkan mencalonkan diri di tingkat lokal.
Perjuangan Maria berlangsung tanpa sorotan nasional. Ia tidak menulis buku best seller, tidak tampil di seminar, dan mungkin namanya tidak pernah disebut di buku cerita anak. Namun, ia menanam benih-benih kemerdekaan perempuan. Termasuk nilai-nilai pendidikan, hak bersuara, dan pemenuhan HAM. Berangkat dari keresahannya menghadapi aturan kolonial yang mempersulit perempuan untuk muncul.
Bagi banyak perempuan lokal di Minahasa, laki-laki maupun perempuan, gagasannya tak hanya membangunkan kesadaran. Ia memberi ruang untuk bertanya, belajar, dan memilih. Kebebasan bagi perempuan.
Maria Walanda Maramis membangun bangsa bukan dengan senjata atau pasukan, tapi dengan kecerdasan, keberanian, dan kematangan. ia mengulurkan tangan ke perempuan-perempuan yang tampak lemah karena tak terdidik, lalu membimbing mereka agar bicara, bergerak, dan mengambil peran.
Membincang kisah Maria, penulis bereflkesi: Seberapa banyak perempuan hari ini yang merasakan jejak dari usaha Maria? Apakah perempuan di kampung, kota, atau desa sekarang diberikan ruang untuk memilih, bersuara, dan belajar tanpa diskriminasi?
Terkadang kemerdekaan perempuan tidak kunjung selesai karena kita merayakannya lewat simbol saja; seminar, ucapan, atau peringatan. Namun, kemerdekaan ialah tentang akses pendidikan, politik, pengambilan keputusan benar-benar setara.
Aku menulis ini supaya suara Maria terdengar lagi, menyusup ke ruang-ruang kecil di mana perempuan masih berjuang dalam sunyi. Tulisan ini bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk menyambung benang perjuangan perempuan hari ini. Kita penting tahu bahwa kemerdekaan bukan soal merdeka dari penjajah saja, tapi soal merdeka dari norma yang mengekang tubuh, suara, dan agensi perempuan.