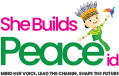Kasus kekerasan seksual banyak merebak terjadi di banyak tempat, ragam kasus, bahkan dapat terjadi pada siapa saja tanpa mengenal status. Kita mungkin sering terheran-heran mengapa ketika satu kasus terungkap dan hukum mulai dijalankan, ternyata masih saja akan berlanjut kasus yang lain. Datang dengan kasus yang beragam dan menuai kejadian yang lebih miris.
Industri hiburan salah satunya film menjadi ruang edukasi—yang dapat menggambarkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada setiap orang termasuk salah satunya perempuan. 27 Steps of May (2018) garapan Ravi Bharwani merupakan salah satu film yang sukses sebagai representasi dampak traumatis korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan dialami oleh anak remaja. Saat menonton film tersebut, kita berusaha untuk diajak melihat dan ikut merasakan bagaimana pengalaman hidup May (remaja korban pemerkosaan) menjadi gambaran korban kekerasan bertahan dalam kelamnya hidup.
Meski begitu, film yang sudah berumur tujuh tahun ini dapat kita jadikan refleksi kesadaran akan gelapnya kasus kekerasan seksual yang masih terus meningkat yang mengindikasikan kuatnya budaya patriarki maupun penindasan pada perempuan itu. Dan mirisnya, belum lama, pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, terkait pemerkosaan 1998 adalah rumor dan tak dapat dibuktikan, telah bertentangan dengan temuan resmi sejarah itu sendiri dan menafikan trauma penyintas.
Meski dalam tulisan ini saya tidak akan membahas itu, tetapi ini menjadi permasalahan kekerasan seksual yang akan lebih kompleks. Sehingga saat film 27 Steps of May hadir, ini memberi pelajaran bagi kita bahwa masa lalu tetap menjadi catatan dan ingatan penting yang kemudian menjadi pelajaran besar bagi seluruh masyarakat. Terlebih sebagai refleksi kesadaran yang harapan besarnya dapat menjadi kekuatan untuk membawa pemahaman utuh atas kebenaran kasus—bukan penyangkalan atas realita.
Sebagai Ruang Berpikir
27 Steps of May menceritakan masalah psikologis yang amat dalam terjadi pada May dan ayahnya sebagai orang terdekat May. May adalah remaja perempuan berumur 17 tahun yang mengalami pemerkosaan gang rape saat bermain di pasar malam. Sejak peristiwa itu, selama delapan tahun May mengalami trauma; hanya hidup di dalam rumah, tanpa bicara, dan hanya melakukan kegiatan mekanis berulang dengan ayahnya.
Perilaku May pun setiap harinya menggambarkan betapa kelamnya kehidupan May yang dihadapi itu. Membantu sang ayah membuat boneka yang dalam boneka itu digambarkan sesuai dengan perasaan atau kondisi May. Begitu pula sajian makanan May yang tampak putih saja berbeda dengan makanan ayah yang lebih berwarna, hingga kegiatan lompat tali setiap malam sebagai ekspresi luapan May.
Tak hanya May, dampak psikis juga dialami sang ayah yang ia lampiaskan saat bertarung di ring tinju. Ayah merasa frustasi dan selalu menyalahkan diri karena menganggap tak bisa menjaga May dengan baik. Peristiwa traumatis yang terjadi pada May juga dapat terbayang lagi saat May dalam keadaan terdesak. Sehingga saat bayangan peristiwa muncul, May lantas melukai lengan tangannya (self harm) untuk melampiaskan sakit dan hancurnya akan ingatan tersebut.
Apa yang dialami May kebanyakan dalam dunia medis digolongkan sebagai Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Tentu, pengidap PTSD akan menjadi masalah dalam hubungan sosial sehari-hari. Bahkan fisik juga dapat terpengaruh sebab pengalaman trauma seseorang akan berpengaruh pada aktivitas normal keseharian. Hidup terasa amat sulit dijalankan secara berkesadaran penuh dan tanpa ambisi dan harapan ke depan. Pengalaman traumatis seseorang pengidap PTSD sangatlah sulit, bahkan bisa memakan waktu begitu lama.
Dalam cerita May, ia nampak mulai berani melihat hidup ke luar saat bertemu dengan pesulap. Aksi pesulap kepada May memberikan hal-hal baru sehingga ia mulai memberanikan diri untuk berinteraksi secara langsung. Maka dari itu, dari film ini mengajarkan bahwa diperlukan tindakan pengobatan dan pemulihan secara tepat untuk mengobati kondisi psikis pengidap dan membantunya pulih kembali dengan kondisi normal.
Pemahaman dan Kesadaran Bukan Penyangkalan
Pelecehan dan kekerasan seksual adalah peristiwa yang mengecilkan kemanusiaan yang bukan hanya akan berdampak pada fisik tetapi psikis juga dapat berakibat akut. Patriarki maupun budaya masyarakat yang jauh dari keyakinan yang benar membuat permasalahan ini mengakibatkan beban besar yang ditanggung penyintas. Di luar sana, pasti masih banyak May yang lain dengan kejadian serupaa atau berbeda, trauma yang besar ataupun kecil, serta mereka butuh penanganan dan pengakuan keberpihakan inklusif dan aman pada korban.
Tentu, sebagaimana Fadli Zon sebagai seorang Menteri Kebudayaan—yang dulu ex aktivis pada masa orde baru tak bisa kita ambil pernyataannya yang denial. Kita butuh pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang harus bersama dicegah kejadiannya dan mau mengakui peristiwanya. Persoalan waktu tak bisa menjadi ukuran bagaimana korban harus “dipaksa” untuk sembuh bagaimanapun caranya.
Hal penting untuk menghargai korban dan mencegah kekerasan seksual berulang adalah dengan kesadaran bahwa peristiwa yang terjadi benar adanya. Sebab menghapus ingatan peristiwa kelam berarti meniadakan nilai kemanusiaan kita pada mereka yang menjadi korban. May juga menjadi gambaran kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia remaja yang dari peristiwa tersebut tentu akan berdampak besar pada masa depan dan caranya melihat dunia yang dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi pada hidup mereka.
Dalam menangani korban anak-anak atau remaja, dalam penelitian Protective Service for Children and Young People Department of Health and community Service (1993), keberadaan dan peran keluarga khususnya orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat penting dalam membantu anak berproses memulihkan diri dan penyesuaian pasca mengalami kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Dari proses pemulihan dari orang tua akan berkaitan dengan resiliensi yang dimiliki orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.
Selain dari upaya penanganan pemulihan korban, akan lebih baik bagi kita dalam melakukan pencegahan dengan memiliki perspektif yang lebih adil dan inklusif dengan pendidikan seksual, pendidikan gender, serta implementasi nilai-nilai perdamaian. Tentu bisa juga dengan kehadiran edukasi yang datang dari industri hiburan termasuk film, sebagaimana 27 Steps of May.