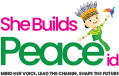Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh tim bentukan Kementerian Kebudayaan mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, salah satunya dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang terdiri dari sejarawan, aktivis kemanusiaan, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Dalam pernyataan tertulisnya, AKSI dengan sangat tegas menolak sejarah resmi yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Menurutnya proyek ini sama saja dengan mengabaikan hak-hak rakyat termasuk para korban untuk mengetahui kebenaran tentang masa lalu.
Selain itu, proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan juga dilakukan dengan cara membungkam suara-suara kritis masyarakat, serta menghilangkan identitas dan memori kolektif rakyat.
Di balik penolakan yang terus disuarakan dengan lantang ini, ternyata ada 2 sejarawan perempuan yang juga ikut terlibat di dalam AKSI, dua di antaranya ialah Ita Fatia Nadia dan Sulistyowati Irianto.
Dalam sesi wawancara bersama jurnalis Magdalene.co, Ita Fatia Nadia yang juga selaku Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan (RUAS) menyampaikan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini bisa menghapus fakta terjadinya pelanggaran HAM berat, menghilangkan peran perempuan dalam sejarah, serta mempersempit ruang diskusi publik.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap agenda tersebut. Selain itu, Ita juga menyoroti tentang peminggiran gerakan perempuan dalam draft proyek penulisan ulang sejarah.
Dari hasil penelitiannya, Ita menemukan bahwa nama-nama seperti Siti Sundari, Surastri Karma Trimurti, Maria Ulfah, Francisca C. Fanggidaej tidak mendapat ruang memadai. Kartini juga hanya sekadar disebut tanpa membahas kontribusinya dalam pendidikan perempuan. Bahkan pelopor pers perempuan Indonesia, Rohana Kudus sama sekali tidak muncul.
Tidak hanya itu, Kongres Perempuan Pertama 1928 hingga peran perempuan dalam Konferensi Wanita Asia Afrika 1950-an juga dihapus. Padahal menurut Ita, momen ini merupakan bagian penting dari sejarah gerakan solidaritas perempuan internasional.
Lebih dari itu, Ita juga sangat menyayangkan karena dalam draft sejarah baru ini pelanggaran HAM berat yang diakui negara justru dihilangkan. Padahal, pada era Joko Widodo, pemerintah telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat.
12 pelanggaran HAM berat tersebut ialah peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, peristiwa Rumoh Geudong, Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999, peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, peristiwa Wamena, Papua 2003, peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Bagi Ita, menghapus pelanggaran HAM berat dari draft sejarah baru ini sama saja dengan mengabaikan hak korban, yakni hak atas keadilan, kebenaran, dan jaminan keamanan di masa depan.
Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Ita mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk terus melawan, salah satunya dengan membuat kontra narasi. Baik lewat tulisan, konten media sosial, diskusi komunitas, penulisan sejarah alternatif, atau publikasi kolektif.
Penulisan Sejarah Menghancurkan Memori Kolektif Rakyat
Masih dalam nafas yang sama, melansir dari Tempo.co, Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum UI yang juga wakil ketua AKSI melakukan penolakan yang sama dengan Ita. Menurut Sulistyowati, penulisan sejarah model ini adalah bentuk pengkhianatan negara terhadap paham kerakyatan dan akan menghancurkan memori kolektif tentang kapasitas alamiah dan kekuatan bangsa, untuk mengatasi tantangan eksistensialnya.
Menurutnya, sejarah tidak boleh dipisahkan dari suara rakyat yang juga menjadi korban kebijakan negara. Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk menjelaskan pengalaman sejarahnya. Terutama pengalaman perempuan dan juga pengalaman para korban pelanggaran HAM di masa lalu.
Tantangan Perempuan Pembela HAM (PPHAM)
Perjuangan para sejarawan menyuarakan hak-hak kemanusiaan dalam proyek penulisan ulang sejarah tidaklah mudah. Dilansir dari Tempo.co, selang beberapa jam setelah menjadi narasumber dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menolak pernyataan Fadli Zon, Ita menerima beberapa teror lewat sambungan telepon.
Pertama, pada Jumat 13 Juni 2025 pukul 20.00, Ita ditelepon oleh orang yang tidak dikenal. Penelepon itu mengancam Ita. “Kamu antek Cina karena bicara perkosaan Tionghoa. Siapa bilang Prabowo terlibat.”
Tidak berhenti begitu saja, pada Sabtu pagi, Ita kembali mendapatkan teror dengan nomor yang sama. Penelepon itu mengancamnya, “mulutmu minta dibungkam selamanya?”
Akibat teror itu, Ita sempat memilih untuk rehat dan tidak menerima permintaan wawancara dari sejumlah media. Ia takut keselamatan diri dan anggota keluarganya terancam.
Apa yang terjadi pada Ita bukan sesuatu hal yang baru. Perempuan-perempuan pembela HAM memang kerap kali mendapatkan ancaman, intimidasi, bahkan sampai pada kekerasan. Terutama ketika ia menyuarakan isu-isu kekerasan seksual. Dalam hal ini, perkosaan massal pada Mei 1998.
Karena itu, selain gerak bersama melakukan aksi penolakan terhadap penghapusan sejarah perempuan dan pelanggaran HAM, kiranya kita juga bisa tetap bergandengan tangan untuk saling jaga dan menguatkan. []