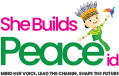Hidup Korban! (Jangan Diam!)
Jangan Diam! (Lawan!)
Suara kerumunan memekik di antara derasnya hujan yang mengguyur Taman Pandang Istana sore itu. Sekitar 100 orang dengan pakaian serba hitam berdiri dan membentuk lingkaran. Sebagian melindungi diri dari air hujan dengan payung, sebagian lain menggunakan jas hujan plastik seperti yang saya kenakan. Aksi ini diadakan hampir setiap Kamis, namun baru kali ini saya menghadirinya secara langsung. Biasanya, saya hanya memantau siaran langsung dari akun Youtube Jakartanicus.
Baik memantau melalui layar ataupun menghadiri secara langsung, ada yang tidak pernah berubah: rasa merinding setiap mendengar orator menyuarakan tuntutan dan argumennya, khususnya Maria Catarina Sumarsih. Hari ini (15 Februari) merupakan Aksi Kamisan yang ke-805. Tujuh belas tahun sudah Sumarsih dan Aksi Kamisan terus bersuara. Atas nama keadilan, atas nama kemanusiaan. Jaringan korban pelanggaran HAM berat di tahun 1998 ini tak lelah mengingatkan. Keadilan dan hukum jangan sampai hanya menjadi produk negara, berjarak dengan masyarakat sipil yang membutuhkannya.
Suara yang Tak Terbalas
Sumarsih, salah satu Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menerima mikrofon dari pemandu. Di tangannya, ia menggenggam surat terbuka nomor 445 yang akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo hari ini. Kertas itu sedikit kusut, mungkin karena cuaca yang sedang hujan. Seorang perempuan berkacamata berdiri di samping Sumarsih, membuatnya teduh di bawah payung hitam.
Perempuan berusia 71 tahun itu membaca baris demi baris surat tersebut. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan banyak lembaga survey, pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat suara tertinggi di atas 57 persen. Sumarsih membaca dengan lantang, “Prabowo adalah mantan Jenderal era orde baru yang belum pernah tersentuh hukum atas keterlibatannya pada penghilanganngangan paksa tahun 1997 sampai 1998.”
Semangat itu disambung oleh Yati, Koordinator Aksi Kamisan. Ia membacakan tuntutan kepada Presiden. Pertama, agar berhenti menggunakan fasilitas negara dan berkolusi dengan penjahat HAM. Kedua, Aksi Kamisan mendesak Jaksa Agung agar segera membentuk tim penyelidikan Ad Hoc. Termasuk di dalamnya, Tim Ad Hoc khusus untuk kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998. Ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ketiga, mereka menuntut jaminan hak korban untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, reparasi, serta jaminan ketidak berulangan peristiwa di masa depan.
Sembari memandang tajam pada mata massa aksi, ia menunjukkan kekecewaannya. “Surat nomor 445 yang ditujukan, dan sampai hari ini tidak mendapatkan satu tindakan yang nyata dan konkrit dari pak Presiden terhadap janji-janjinya untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAMham berat di negara ini.”
Tahun demi tahun berganti, namun hukuman tidak pernah dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran HAM. Jangankan mendapatkan hukuman, kasus-kasus ini tidak pernah sampai di meja hijau. Inilah yang disebut impunitas. Kekebalan sebagian orang atas hukum yang berlaku. Surat-surat yang dikirimkan seakan angin lalu. Padahal, surat itu adalah suara mereka yang merindukan keadilan bagi para korban.
Teguh Menolak ‘Cara Kekeluargaan’
Keadilan, barangkali menjadi kata yang hampir seperti mimpi bagi pejuang di Aksi Kamisan. Bagaimana tidak, sejak 2007 hingga 2024, tidak pernah satu kali pun massa aksi ditemui Presiden. Dari periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga dua periode Presiden Jokowi. Selayaknya tamu yang tak pernah diharapkan. Malahan, setiap Kamis dijaga ketat oleh barisan aparat. Berdirinya massa di tempat yang sama selama 17 tahun, menandakan proses pemenuhan keadilan yang tidak kunjung beranjak ke mana-mana.
Kisah berawal di tahun 1998. Pada tragedi Semanggi I (13-15 November 1998), dua belas orang meninggal. Di antaranya, putra dari Sumarsih, Wawan. Pada tragedi Semanggi II, sebelas orang meninggal, dan 217 orang luka-luka. Ribuan keluarga tersakiti karena tragedi itu dan pelanggaran HAM berat lainnya. Mereka kemudian mengambil berbagai langkah hukum, mencari keadilan bagi keluarganya.
Setelah Tragedi Semanggi I dan II, audiensi kepada Komnas HAM terus dilakukan. Komnas HAM kemudian membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM. Hingga di tahun 2002, berkas penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Namun, dalam satu tahun empat kali berkas dikembalikan dengan berbagai alasan. Pengembalian ini berujung pada penolakan penyidikan pada tanggal 11 Maret tahun 2003.
Sumarsih dan keluarga korban lainnya membawa kasus ini ke DPR. Pada tahun 2004, justru DPR menyatakan peristiwa tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pada masa periode kedua SBY, dibentuk Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM masa lalu. Sumarsih bersama JSKK menolak langkah tersebut, karena langkah tersebut merupakan proses penyelesaian kasus non-yudisial.
Satu waktu, Albert (mantan KPP Komnas HAM yang kala itu menjabat Wantimpres) mengusulkan Presiden agar meminta maaf. Sumarsih tegas menjawab, “Maaf itu tidak perlu. Kalau menurut saya yang penting itu perubahan perilaku.”
Hingga pada masa kampanye Presiden Jokowi tahun 2014, mereka mendapatkan sedikit harapan. Nawacita yang menjadi program pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla menulis satu per satu 12 tragedi pelanggaran HAM berat. Tak lama setelah dilantik, harapan itu purna kala Jokowi melantik Wiranto menjadi Menkopolhukam. Pernah mereka bertemu langsung dengan Presiden Jokowi pada 31 Mei 2018, menyerahkan draf penyelidikan dan hanya kembali menerima janji.
Saya menghela napas panjang saat membaca langkah-langkah advokasi yang dilalui JSKK sejak 1998. Dari berkas 99/G/2020/PTUN-JKT dari PTUN Jakarta, saya melihat bahwa upaya dengan jalur hukum saja menghadapi banyak sekali tantangan. Apalagi jika diselesaikan secara non-yudisial?
Maka saya mengerti mengapa Sumarsih dan JSKK teguh menolak penyelesaian non-yudisial. Mulai dari Dewan Kerukunan, Tim Terpadu, santunan, dan lainnya. Pengadilan Ad-Hoc yang semestinya dibentuk oleh Kejaksaan Agung sejak 2007 tidak pernah ada. Ratusan surat terbuka oleh JSKK selalu mengulang permohonan ini. Namun biar ribuan kali diucapkan, suara mereka tak pernah menembus tembok Istana Negara.
Resiliensi Sumarsih dan Aksi Kamisan
Suara Sumarsih mungkin tidak menembus pemangku kepentingan, namun berhasil menjadi peluru bagi banyak anak muda. Keberanian Sumarsih dan JSKK tumbuh di puluhan kota lain. Keberanian untuk bersuara. Keberanian untuk tegak melawan. Keberanian untuk berjuang.
“Setiap Kamis, kami mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Tuntutan kami bermacam-macam. Semua permasalahan rakyat. Baik yang belum ditangani oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di negara kita, saat ini ada 65 kota yang menyelenggarakan aksi kamisan. Kami saling bahu membahu bekerja sama untuk menyuarakan permasalahan rakyat.”
Keberulangan konflik HAM di Indonesia terus terjadi, seiring berdirinya Sumarsih dan Aksi Kamisan. Ruang yang telah dibuka oleh Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung menjadi corong suara korban. Mereka hanya bisa berlindung di balik payung hitam, karena hukum belum pernah terbukti melindungi mereka.
“Aksi kamisan ini adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, dan menolak lupa,” perempuan berambut putih itu tidak main-main dengan kata-katanya.
Kata-kata Sumarsih tertancap dalam di kepala dan hati saya. Pantas banyak anak muda tergerak dengan semangatnya. Seorang perempuan pejuang HAM, seorang ibu, dan kini bagi saya seorang guru. Kegigihan Sumarsih berhasil mengajarkan pada saya, bahwa kasih sayang atas kemanusiaanlah yang merawat bangsa. Bukan kekerasan, apalagi impunitas.