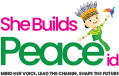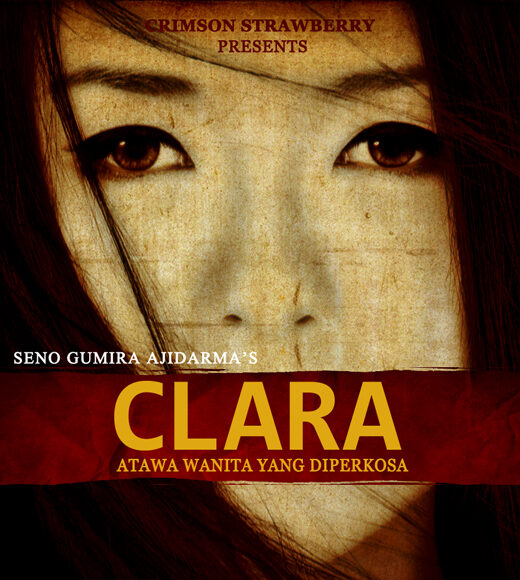Tahun 1998 silam, Seno Gumira Ajidarma, menulis sebuah cerpen berjudul “Clara atawa Wanita yang Diperkosa”. Kala itu, diksi wanita masih jamak dipakai. Jadi, wajar jika Seno masih menggunakan kata wanita alih-alih perempuan. Padahal di era Orde Baru, konotasi wanita sering dikaitkan dengan urusan domestik, tidak mandiri dan minim kontribusi. Hingga akhirnya, diskursus ini memicu pergerakan di kalangan perempuan.
Organisasi seperti Solidaritas Perempuan bahkan Komnas Perempuan memilih kata ‘perempuan’ yang secara etimologis berarti mulia atau terhormat. Sedangkan kata wanita merujuk kepada sikap yang harus lemah gemulai, sabar, halus, tunduk, patuh, mendampingi dan menyenangkan pria.
Presiden Abdurrahman Wahid pun mengubah nama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Hal ini menandakan bahwa kata ‘perempuan’ dianggap lebih tepat dan kuat terutama dalam isu kesetaraan.
Terlepas dari diskursus gender, Seno Gumira Ajidarma melalui cerpennya berusaha mengungkapkan fakta yang terjadi terhadap kelompok etnis Tionghoa pada Mei 1998.
Cerpen berjudul Clara atawa Wanita yang Diperkosa mengisahkan tentang tokoh Clara yang sedang berada di perjalanan pulang seusai mengurus bisnis di luar negeri. Ia mendapat kabar dari orang tuanya jika terjadi kerusuhan di Jakarta dan menargetkan kelompok etnis Tionghoa. Jadi, keluarga Clara yang berdarah Tionghoa memintanya pergi ke Singapura atau Sydney, Australia.
Tetapi, Clara tidak mau meninggalkan mereka. Mobil yang ia kendarai tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Mereka menjarah dan memerkosa Clara karena ia etnis Tionghoa.
Sebangunnya dari pingsan, seorang ibu-ibu memberikan Clara pakaian. Ironisnya, saat itu pula, ia menerima kabar kalau kedua adiknya diperkosa lalu dibakar hidup-hidup ke dalam kobaran api. Sementara sang ibu yang juga diperkosa memilih bunuh diri. Sang ayah yang mengabari Clara juga berniat mengakhiri hidup.
Clara yang berusaha mencari keadilan melapor kepada pihak berwenang. Sayangnya, aparat justru menghardik dan menyangsikan bukti yang menyiratkan jika Clara adalah korban pemerkosaan. Setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya aparat sengaja membungkam Clara lantaran terdapat perintah dari atasan. Lantaran saat itu banyak kasus serupa sehingga khawatir terendus wartawan dan LSM.
Melawan lewat Kata
Pada tahun 1997, sebelum menulis cerpen Clara, Seno berujar “Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara.” Langkah ini sengaja ditempuh karena saat itu banyak koran dan majalah dibredel, dan wartawan mengalami intimidasi. Selain itu, media fiksi dipilih karena bisa menyuarakan nurani. Meski buku fiksi dibredel bahkan dibakar, suara nurani akan selalu mengudara. Berbeda dengan produk jurnalisme yang terikat aturan, dan bukan berasal dari nurani. Pakem ini harus ditaati karena melibatkan fakta.
Sayangnya, fakta bisa dimanipulasi, dan ditutup dengan tinta hitam. Terlebih jika disandingkan dengan politik. Fakta bisa ditutupi atau dihilangkan. Akhirnya, sebagian jurnalis menggunakan fiksi sebagai media alternatif agar suara lantang tidak lagi sumbang.
Maka, tidak salah, jika menyebut Clara sejatinya kisah nyata yang sengaja Seno abadikan lewat fiksi. Terlebih pada tahun 1998 silam, banyak perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual. Tubuh para perempuan ini sengaja dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan.
Mereka tidak hanya dihancurkan sebatas fisik, tapi juga secara politik identitas. Mereka diperkosa karena dianggap sebagai ‘kelompok lain’ sehingga layak dijarah, dilukai, dan dikorbankan atas nama kebencian berbalut rasisme belaka. Dalam konteks ini, kekerasan seksual digunakan sebagai pesan politik.
Akibatnya, publik menekan pemerintah untuk mengusut tuntas kejadian ini. Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan merespon dengan menggagas kampanye bertajuk Signatory Campaign. Dalam 2 pekan, terkumpul tanda tangan dari beragam kalangan. Bahkan, Presiden B.J. Habibie kemudian membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Hasilnya, mereka menemukan 52 perempuan menjadi korban pemerkosaan; 14 orang diperkosa dan dianiaya; 10 orang mengalami penyerangan seksual; dan 9 perempuan mengalami pelecehan seksual. Fakta inilah yang mendorong Presiden B.J. Habibie untuk menyetujui pembentukan Komnas Perempuan. Tidak cukup sampai di sini, Presiden B.J. Habibie juga mengakui dan mengutuk kejadian ini.
“Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga di bumi Indonesia, pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.”
Meski angka yang disodorkan TGPF memang jauh dari representasi secara keseluruhan, namun angka ini adalah bukti bahwa pemerkosaan itu ada. Kekerasan seksual justru seringkali digunakan sebagai taktik perang untuk melemahkan lawan saat konflik terjadi.
Absennya Perspektif Korban dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Tahun ini, pemerintah memiliki agenda menulis ulang sejarah Indonesia. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT NKRI ke-80. Namun, dalam sebuah wawancara yang dipimpin Redaksi IDN Times, yaitu Uni Lubis dengan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, luka 27 tahun lalu itu kembali tersayat.
Alih-alih mempertanyakan bagaimana perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan seksual, ia malah mengatakan jika pemerkosaan massal tahun 1998 itu sebatas rumor, bukan fakta. Alasannya karena tidak ada bukti kalau peristiwa itu benar-benar terjadi.
Pernyataan ini dapat dilihat di channel Youtube IDN Times. Publik pun geram. Banyak pihak yang mengecam. Media sosial gaduh. Meski pada akhirnya statement tersebut diklarifikasi, tetap saja publik melihat adanya upaya pelenyapan sebuah fakta.
Apalagi dalam klarifikasinya, Fadli Zon menyebut jika sebenarnya ia mengakui peristiwa itu terjadi, namun tidak setuju dengan diksi ‘massal’. Sontak publik kian bertanya-tanya, mengapa sedikit banyaknya angka yang merujuk terhadap jumlah korban, pada akhirnya menjadi alat negara untuk terus menyangkal?
Terlebih perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan seksual masih jauh dari agenda prioritas negara. Sampai detik ini, pengalaman para korban tidak benar-benar diakui. Trauma mereka belum kunjung pulih.
Padahal setidaknya dengan mengabadikan kisah pemerkosaan massal Mei 1998 ke dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, negara mengakui pengalaman korban, sehingga negara wajib hadir memenuhi hak warganya.
Sayangnya, negara selalu berusaha menyela fakta. Barangkali jalan satu-satunya untuk mengakui keberadaan para korban ini hanya lewat fiksi. Dengan begitu, kebenaran itu akan terus mengudara.