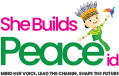“Belajarlah untuk hidup komunal. Jika Anda adalah orang tua, ajarkan anak Anda untuk hidup komunal sejak kecil. Saat mereka besar nanti, empatinya akan lebih terasah. Jika Anda adalah seorang remaja, hal ini akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk belajar dan melatih kepekaan diri guna menjadi seorang changemaker.” – Sri Wahyaningsih
Pengalaman hidup komunal ketika tumbuh bersama anak-anak dan keluarga pekerja saat lahir dari keluarga pengusaha di Klaten, telah menanamkan nilai empati yang begitu besar. Usai menikah dengan seorang aktivis organisasi non-pemerintah di Yogyakarta, Toto Rahardjo, Wahya berhenti bekerja. Karena Toto mendapat tugas di luar Jawa, dia pulang ke rumah mertuanya di Desa Lawen, Banjarnegara, Jawa Tengah.
Desa di kaki gunung itu mengawali, perjalanan Wahya dalam bidang pendidikan. Hatinya terketuk melihat banyak anak putus sekolah, penduduk usia produktif keluar dari desa. Tanah yang subur, tak membuat masyarakat setempat tertarik untuk memanfaatkannya, termasuk tak mampu menahan kepergian anak muda ke luar dari desa, merantau mencari kerja di kota.
Mengamati hasil ladang dan sawah di Lawen yang bervariasi, mulai kopi, teh, singkong, kayu, kolangkaling, gula, sayuran dan sebagainya, sebenarnya menunjukkan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Namun, Wahya merasa heran mengapa masyarakat di sana tergolong miskin. Setelah melalui perenungan dan riset kecil-kecilan, Wahya menemukan penyebab kemiskinan itu.
Pendidikan yang tidak mengakar, ternyata menjadi kendala utama masyarakat Lawen tertinggal saat itu. Seperti kata Romo Mangun, bahwa perguruan tinggi itu penting, tapi pendidikan dasar jauh lebih penting. Wahya juga menemukan para orang tua di Lawen menganggap sekolah sebagai sebuah ‘barang’ mahal yang tidak memberi perubahan secara cepat, karena saat tamat sekolahpun, anak-anak masih harus bersaing, masuk dalam kompetisi dunia kerja. Sementara dengan membantu orang tua di sawah atau ladang, anak-anak sudah berlatih untuk bekerja, dianggap siap bekerja, tidak perlu susah-susah bersaing lagi dengan orang lain.
“Ada juga penduduk desa yang berpikir, sekolah justru menjauhkan anak-anak dari realita. Jika orang tua adalah seorang petani, dengan bersekolah, si anak enggan turun dan membantu orang tuanya di sawah. Dengan alasan takut akan mengotori seragam sekolah mereka. Belum lagi yang berhenti sekolah karena pernikahan dini yang nantinya berefek pada kehamilan di usia muda, dan kematian ibu saat melahirkan,” urai Wahya tentang kenyataan di Lawen.
Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, Wahya merasa perlu memberi pemahaman pada orang tua tentang konsep dari pendidikan atau pembelajaran.
“Padahal belajar itu tidak hanya duduk di sekolah saja. Di ladang pun sebenarnya mereka bisa dikatakan belajar juga,” tutur Wahya, sembari menyusun strategi mengumpulkan anak-anak dengan merogoh kantung sendiri, sepulang dari mereka sekolah. Hanya menggunakan fasilitas tanah milik mertuanya, mulailah Wahya membangun Sanggar Anak Alam.
Mereka dilatih banyak hal, belajar dari sekitarnya, melakukan riset kecil-kecilan, mulai dari memelihara kambing, kelinci sampai belajar ngarit (menyabit rumput). Proses inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Sanggar Anak Alam (SALAM) tahun 1988 yang berlokasi pertama di Lawen, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kondisi mertua yang lama menjabat sebagai lurah dan menjadi penyemangat warga setempat menjadi penguat motivasi Wahya, apalagi mengingat Toto suaminya sedang bertugas di NGO non pemerintah di NTT.
Awal mula Salam di Lawen direspons sangat baik. Hanya lima belas anak yang menaruh minat untuk belajar. Tak disangka, dalam hitungan hari, jumlah anak bertambah terus hingga 160-an orang, dengan 40 anak diantaranya juga ikut tinggal bersama Wahya. “Saya katakan pada mereka kalau kita ingin punya sesuatu, kita pasti bisa membuat sesuatu,” pesan Wahya yang ternyata memotivasi anak-anak rajin datang kembali.
Pesan itu lantas diwujudkan dengan membuat berbagai penganan dari hasil pertanian dan perkebunan setempat. Berbagai jenis makanan berbahan dasar singkong, pisang dibuat keripik, tape, kue, dll. Hingga tujuh bulan, uang yang didapat bisa mencapai nominal satu juta rupiah. Wahya pun mengatur agar anak-anak tetap sekolah pada pagi harinya, siang hari berkegiatan mengolah makanan, terutama untuk persiapan keesokan pagi, dititipkan di warung-warung sebelum berangkat sekolah. Lambat laun, orangtua yang tadinya hanya duduk-duduk saja mengamati, satu per satu ikut bergabung.
Melihat antusiasme orang tua, Wahya menginisiasi warga memproduksi sapu karena bahan baku sangat melimpah yang dijual keluar sampai ke kota. “Saat itu di Lawen belum ada aliran listrik. Warga menggunakan diesel yang dihidupkan sejak jam enam sore hingga sebelas malam. Masyarakat memanfaatkan penerangan itu untuk membuat sapu. Otomatis, pada jam itu mereka produktif dan berhenti sejenak merokok. Dengan begitu, hidup lebih produktif, lama kelamaan ekonomi masyarakat jadi membaik,” tutur Wahya.
Perubahan dan ajakan untuk mengubah pola pikir terus dilakukan. Pernah terjadi protes dari orang tua yang tidak terima jika anaknya diajak bergabung dengan SALAM karena menjadikannya berhenti dari kewajiban ngarit yang ditetapkan orang tua. Bukannya berkecil hati, justru Wahya memanfaatkan peluang itu untuk melakukan mediasi. Upaya berdialog itu belakangan malah menjadi kegiatan rutin, yang dinamakan ajang temu wicara setiap malam Sabtu Wage.
Ketika ruang dialog dibukakan, persoalan kemiskinan kembali terkuak. Betapa tidak, anak kelas 2 hingga kelas 5 SD wajib ngarit setiap pulang sekolah untuk mengumpulkan uang membeli kambing, minimal lima ekor untuk persiapan sunat dan hajatan yang menyertainya. Dalam dialog setiap penanggalan Sabtu Wage itu, Wahya mengungkapkan keberatannya tentang ketidakharusan hajatan besar-besaran untuk sunat, kalau hanya untuk menuruti keinginan pencapaian status sosial, dengan kata lain seperti apa kemauan masyarakat.
Sebab, kenyataannya ketika hajatan usai, warga masih harus melunasi hutang yang lalu menjadikan terbelit sistem ijon. “Mengapa demi kebanggaan orang tua, melakukan hal yang tidak adil bagi anak?” tanya Wahya kepada warga setempat.
Sejak saat itulah, warga menjadi berpikir ulang untuk melakukan tradisi potong kambing lima ekor untuk pesta sunatan tersebut.
Salam di Lawen menjadi media Wahya mengimplementasi dan elaborasi konsep ‘desa’ dan ‘alam semesta’, menjadi media belajar sekaligus sekolah, dengan kelompok perempuan yang menjadi pengajar sukarela, yang tak disangka kelak berperan menjadi pelaku penting bagi pendidikan anak-anak. Bahan ajar yang berasal dari permasalahan dan situasi nyata, menjadi sangat relevan, apalagi beberapa proyek siswa seperti pengolahan pangan dan pengembangbiakkan hewan ternak membantu siswa menjadi percaya diri karena ikut memberi sumbangsih bagi perekonomian desa.
Di Lawen, Wahya mendorong ibu-ibu membuat beberapa kelompok kerja: membuat bubuk kopi hitam (awalnya cuma dijual biji), membuat kue satu berbahan dasar beras ketan dan gula aren dan mengolah teh hitam untuk siap dipasarkan. Selain dijual di Lawen dan sekitarnya, tamu-tamu dari luar kota bahkan luar negeri yang berkunjung ke Lawen antusias membeli produk tersebut. Wahya pun melakukan audiensi agar mendapat bantuan relawan dari Yogya, yang bisa membantu memasarkan produk desa untuk layak dijual di beberapa toko di Yogya dan Bali.
Sementara itu, para bapak mulai tersentuh hatinya untuk membentuk kelompok tani. Mereka mengerjakan ladang/sawah secara berkelompok sehingga kebutuhan sayur mayur mulai dapat tercukupi. Beberapa kelompok sampai hari ini masih ada. Bahkan mereka pun inisiatif membuat kelompok simpan pinjam untuk menghindari pengijon. Dari usaha tersebut sedikit banyak perekonomian masyarakat desa makin membaik.
Kerja-kerja yang dilakukan oleh Bu Wahya di Lawen menunjukkan bagaimana aktivisme pelbagai bidang, mulai sosial, politikal, dan kultural yang digerakkan lewat komunitas terkecil bisa berdampak besar.
“Tak perlu keluar dari desa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik,” tutur Wahya mengakhiri cerita tentang Lawen.