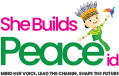Perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya ditorehkan oleh tokoh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang menorehkan jejak penting dalam sejarah. Salah satu figur yang paling menonjol adalah Cut Nyak Dhien, pahlawan nasional asal Aceh yang lahir pada 1848 di Lampadang, Aceh Besar.
Dalam konteks kolonialisme Belanda, Dhien bukan sekadar pendamping suami, melainkan seorang pemimpin militer, ahli strategi, dan simbol perlawanan yang menentang struktur kekuasaan kolonial. Artikel ini menelaah perjalanan hidup, kepemimpinan, serta signifikansi perjuangan Dhien dalam bingkai kemerdekaan Indonesia dan relevansinya terhadap wacana kontemporer tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.
Latar Belakang Sosial dan Politik Aceh
Pada pertengahan abad ke-19, Aceh masih merupakan kesultanan yang kaya dan strategis, terutama dari hasil perdagangan lada. Letaknya di jalur Selat Malaka menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan internasional, sehingga Aceh sering disebut sebagai “Serambi Mekkah” sekaligus benteng penting di Asia Tenggara. Namun, kekuatan ekonomi ini juga memicu kepentingan kolonial Belanda untuk menaklukkannya, yang kemudian melahirkan Perang Aceh pada 1873 (Reid, 2005).
Dalam struktur sosial Aceh, perempuan tidak sepenuhnya termarginalisasi. Tradisi kepemimpinan perempuan telah ada sejak abad ke-17, seperti Sultanah Safiatuddin Syah (1641-1675). Konteks ini membuka ruang bagi figur seperti Cut Nyak Dhien untuk tampil di ranah publik. Kehadirannya dalam barisan kepemimpinan perang menegaskan bahwa peran perempuan di Aceh bukan pengecualian, melainkan bagian dari warisan politik-budaya yang relatif egaliter.
Peran Dhien dalam Perlawanan Aceh
Keterlibatan Dhien dalam perlawanan dimulai setelah suaminya, Teuku Cek Ibrahim Lamnga, gugur pada 1878 dalam pertempuran melawan Belanda. Kehilangan itu tidak mematahkan semangatnya, melainkan menumbuhkan tekad untuk melanjutkan perjuangan. Ia kemudian menikah dengan Teuku Umar, seorang panglima perang Aceh, yang memperkuat posisinya dalam perlawanan.
Bersama Teuku Umar, Dhien tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai penasihat strategis dan penggerak moral. Strategi gerilya yang mereka jalankan menggabungkan pengetahuan medan, jaringan sosial, serta legitimasi agama. Dalam berbagai catatan, Dhien kerap digambarkan memberikan orasi di hadapan pasukan, membangkitkan semangat jihad melawan kolonialisme. Ia memosisikan perjuangan Aceh bukan hanya sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai perlawanan moral dan spiritual (Djajadiningrat, 1984).
Kepemimpinan Strategis dan Konsistensi
Dalam strategi militer, Dhien menunjukkan kecerdasan politik yang jarang diakui pada perempuan abad ke-19. Saat Teuku Umar berpura-pura menjalin kerja sama dengan Belanda untuk memperoleh persenjataan, Dhien memainkan peran kunci dalam menjaga kepercayaan rakyat Aceh agar tidak terpecah. Manuver ini kemudian menjadi salah satu taktik paling cerdas dalam sejarah perang kolonial di Nusantara.
Setelah Umar gugur pada 1899, Dhien melanjutkan perjuangan dengan pasukan kecil di pedalaman Aceh. Kondisi fisiknya semakin menurun karena usia tua, rabun, dan penyakit rematik, tetapi ia menolak menyerah. Kepemimpinan Dhien di tahap ini memperlihatkan konsistensi: perlawanan tidak semata bergantung pada figur suami atau panglima laki-laki, melainkan pada keyakinan mendalam terhadap kemerdekaan.
Pada 1901, salah satu panglimanya, Pang Laot, membocorkan lokasi persembunyian Dhien karena iba melihat kondisi fisiknya. Ia pun ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya, Dhien tetap dihormati masyarakat setempat, bahkan dikenal dengan sebutan “Ibu Perbu” karena ketokohan dan kebijaksanaannya. Ia wafat pada 6 November 1908, jauh dari tanah kelahirannya, tetapi jejak perjuangannya terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa.
Signifikansi dalam Narasi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Cut Nyak Dhien memiliki tiga signifikansi utama dalam narasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, rekognisi kepemimpinan perempuan. Dhien membuktikan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme bukan monopoli laki-laki. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat memimpin, berstrategi, dan memobilisasi kekuatan rakyat.
Kedua, dimensi moral-spiritual. Perlawanan Dhien tidak hanya bertujuan politik, tetapi juga dibingkai sebagai jihad melawan penindasan. Dimensi religius ini memperkuat semangat rakyat Aceh yang melihat perang sebagai panggilan suci.
Ketiga, mendorong partisipasi perempuan. Perjuangan Dhien menantang narasi sejarah Indonesia yang sering menempatkan perempuan dalam posisi sekunder. Keberaniannya menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat tercapai ketika perempuan memiliki ruang gerak yang setara dalam menentukan arah bangsa.
Cut Nyak Dhien, tokoh pahlawan nasional yang melampaui zamannya. Ia bukan hanya pendamping seorang panglima, melainkan pemimpin, pengatur strategi, dan simbol keberanian perempuan Indonesia. Dari medan perang Aceh hingga pengasingan di Sumedang, warisan Dhien menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan utuh tanpa mengakui peran perempuan sebagai aktor utama.
Dalam konteks Indonesia modern, refleksi atas perjuangan Dhien penting untuk memastikan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari kolonialisme, tetapi juga sebagai ruang partisipasi setara bagi perempuan dalam perdamaian, politik, dan pembangunan nasional.