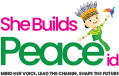Meskipun kita sepakat menjadikan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, namun faktanya konflik kesukuan masih sering terjadi. Sikap primordialisme masih dipertahankan demi mendapatkan pengakuan bahwa bangsa atau suku, atau ras nya adalah yang terbaik dibanding dengan yang lainnya. Tak ada keuntungan yang didapat, kecuali hanya kerugian dan keterpecahbelahan.
Menang jadi arang, kalah jadi abu adalah peribahasa yang cocok untuk menggambar situasi konflik berdasarkan ras tersebut. Belum lagi dampak yang dirasakan oleh perempuan dan anak-anak di tengah konflik rasial. Perempuan dan anak akan merasakan beban ganda sebagai akibat dari konflik yang terjadi. Perempuan dituntut untuk tetap di rumah untuk melindungi anak, dan di satu sisi ia harus tetap memenuhi kebutuhan perut di tengah desingan peluru perang. Belum lagi dampak traumatis yang dirasakan oleh anak-anak.
Lantas seperti apa konflik rasial yang pernah terjadi di Indonesia? Dan bagaimana dampaknya bagi perempuan?. Berikut ini akan disampaikan kajian mengenai konflik ras Papua di Surabaya pada tahun 2019 dan juga konflik agama di Sigi Sulawesi Tengah pada November 2020.
Konflik Rasial di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya
Sehari menjelang peringatan kemerdekaan RI 3 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa sejarah yang tak terlupakan. Jumat, 16 Agustus 2019, asrama mahasiswa Papua di Surabaya di kepung oleh ratusan masa. Hal ini berawal dari beredarnya sebuah foto melalui media whatsapp. Seorang mahasiswa Papua mematahkan tiang bendera merah putih dan dilanjutkan dengan membuang bendera ke selokan.
Sebanyak 43 mahasiswa Papua dikepung dan dimaki dengan ujaran rasisme. Mereka digelandang dan ditahan di Polrestabes Surabaya. Setelah penyelidikan, penegak hukum tidak mampu membuktikan siapa pelaku perusak bendera tersebut. Sedangkan pelaku ujaran rasisme yang aktif memprovokasi pengepungan mahasiswa Papua, mendapatkan hukuman 5 dan 7 bulan penjara.
Peristiwa ini memicu demonstrasi di Papua dan Papua Barat. Mereka menuntut pelaku rasisme di Surabaya diberi hukuman yang setimpal. Akibat demo tersebut, sebanyak 6 aktivis HAM di tangkap dan dijadikan tawanan politik. Mereka adalah Ariana Elopere, Paulus Suryanta Ginting, Ambrosius Mulait, Charles Kossay, Dano Anes Tabuni dan Isay Wenda. Hingga pada 12 Mei 2020, keenam tawanan tersebut mendapat asimilasi dan integrasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan dibebaskan bersyarat.
Hal lain dialami oleh Norince Kogoya, mahasiswi STIK Sint Carolus di Jakarta. Ia dinyatakan drop out dan tidak lagi tercatat sebagai mahasiswi STIK Sint Carolus karena mengikuti aksi menolak rasisme Papua di Jakarta. Norince sempat dipanggil pihak kepolisian atas aksi yang ia ikuti, namun Norince tak menyangka dirinya harus mendapatkan sanksi DO dari pihak kampus. Saat dikonfirmasi, pihak STIK Sint Carolus menyatakan sanksi DO Norince tidak berkaitan dengan keikutsertaannya dalam demo melawan rasisme Papua di Jakarta.
Dampak konflik terhadap perempuan, Kembali Ke Masa Orde Baru?
Berkaca dari kasus konflik rasial mahasiswa Papua di Surabaya, perempuan mengalami dampak yang lebih serius dibanding yang lainnya. Dalam kasus Norince Kogoya misalnya, ia harus menerima sanksi drop out dari kampusnya karena keikutsertaannya dalam demo melawan rasisme. Sanksi yang dialami Norince Kogoya berkaitan dengan persepsi yang dikonstruk Orde Baru atas gerwani.
Pada tahun 1965, Gerwani dibubarkan karena dianggap berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Secara otomatis, gerakan perempuan yang tadinya massif memperjuangkan kesetaraan gender menjadi mati suri. Muncul kekhawatiran dianggap sebagai “organisasi kiri” jika terus menuntut pada rezim. (Ruth:1996)
Simbol-simbol mengenai seks liar dan kastrasi digunakan untuk memberangus keberanian perempuan, kemandirian sosial politik, dan otonomi. Hal yang di kemudian hari menyisakan bencana panjang sejarah perempuan di Indonesia. Pemerintah militer Orde Baru yang pro modal berhasil menghilangkan Gerwani dari sejarah gerakan perempuan (Soyomukti, 2009).
Perempuan baik yang dikonstruk Orba adalah perempuan yang menghabiskan waktunya bersama anak-anak dirumah, bukan di tempat kerja, apalagi ikut menyuarakan aspirasinya pada bidang politik. Perempuan dilarang masuk dalam politik praktis, kecuali jika suaminya adalah politisi. Itupun posisinya hanya sekedar menjadi pendamping pelantikan, pendamping kunjungan kerja. Tidak ada perlawanan terhadap diksriminasi dan ekspolitasi yang dialami perempuan, karena perlawanan dianggap sebuah pemberontakan dan penyalahan atas kodrat perempuan.
Organisasi perempuan mengalami domestikasi dan pengebirian yang massif. Perempuan tak lagi menjadi manusia merdeka yang bebas mengekpresikan ide-idenya untuk kemajuan perempuan dari sisi perempuan. (Hubies: 2001). Meskipun sudah memasuki era reformasi yang “katanya” terbuka terhadap kritik, namun pemikiran yang kuno dan kolot tentang gerakan perempuan nyatanya belum sepenuhnya hilang. Sehingga keikutsertaan Norince Kogoya dalam demo melawan rasisme Papua di Jakarta dianggap sebagai sebuah ketidakwajaran sebagaimana gerakan Gerwani dalam konstruksi Orba.