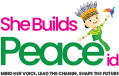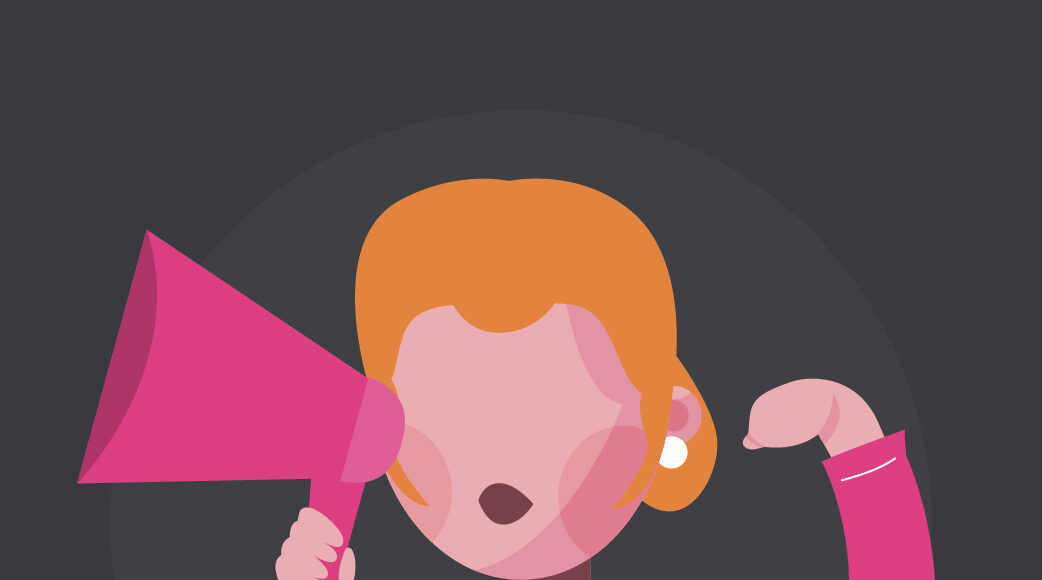Dua puluh tujuh tahun berlalu sejak pemerkosaan massal yang memilukan terjadi pada Mei 1998. Negara, melalui Menteri Kebudayaan, justru menyangkal peristiwa tersebut, “pemerkosaan massal kata siapa itu? nggak ada proof-nya. Itu adalah cerita,” ujarnya dalam wawancara dengan media IDN Times yang tayang di YouTube pada Rabu, 11 Juni 2025.
Padahal, B.J Habibie, presiden Republik Indonesia saat itu, mengakui benar adanya pemerkosaan massal dengan bukti-bukti yang dikumpulkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam “Seri Dokumen Kunci 2: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998” yang dapat diakses publik di situs resmi Komnas Perempuan.
Ialah Fransiska, anak perempuan Tionghoa berusia 11 tahun, satu dari sekian bukti pemerkosaan massal Mei 1998. Kisah Fransiska dapat dibaca dalam artikel Tempo berjudul Kisah Fransiska, Bocah Korban Pemerkosaan Massal 1998 di situsnya pada 25 Juni 2025.
Fransiska adalah anak dari keluarga Tionghoa peternak babi di kawasan Pasar Lama, Tangerang. Saat kejadian memilukan itu, ayahnya sedang pergi ke Lampung untuk urusan pekerjaan. Sekelompok pemuda memperkosa Fransiska setelah sebelumnya membunuh ibu dan kakak perempuannya.
Dilansir dari artikel Tempo berjudul Cerita Korban, Pendamping, dan Tim Investigasi tentang Pemerkosaan Massal 1998 yang tayang di situsnya pada 22 Juni 2025, Ita Fatia Nadia, Koordinator Tim Relawan Kemanusiaan untuk Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP), menuturkan ceritanya kepada redaksi Tempo.
“Ibu dan kakak perempuannya dibunuh lebih dulu, kemudian Fransiska meninggal di pangkuan saya dengan kondisi vagina yang rusak,” kata Ita. “Ada pecahan beling di sekitar vulvanya,” tambahnya. Dalam artikel Tempo tersebut, disebutkan saat pertama ditemukan, Fransiska sempat dilarikan ke sebuah klinik. Di sana Ita senantiasa menemaninya sampai Fransiska menghembuskan napas terakhir.
Tubuh dan cerita Fransiska—juga korban pemerkosaan lainnya—berulang kali dibungkam, tapi saya percaya kebenaran pasti terungkap. Di suatu tempat, di suatu waktu, seseorang yang kita tahu atau mungkin tidak kita tahu punya suatu cara untuk mengungkapkannya.
Keadilan yang sampai hari ini belum tampak di depan mata bagi para korban pemerkosaan Mei 1998 masih terus digaungkan oleh orang-orang yang terus berdiri di sisi korban. Orang-orang ini menyuarakan hak-hak korban dengan berbagai cara, salah satunya melalui karya seni.
Perlawanan Melalui Karya Seni Puisi
Ialah Cyntha Hariadi, penulis dan penyair perempuan Indonesia, yang dengan berani menyulam kisah Fransiska dalam satu puisinya. Cyntha memang bertujuan mengangkat kisah kerusuhan Mei 1998 berikut pemerkosaan massal yang menyertainya dan kelindannya dengan rasisme terhadap etnis Tionghoa kala itu.
Puisi-puisi yang ia tulis dalam rentang tahun 2016-2020 dibukukan dalam sebuah buku kumpulan puisi berjudul “CICA” dan telah memenangkan Penghargaan Sastra Badan Bahasa Kemendikbud 2024.
Menariknya, 96 puisi dalam buku ini tidak berjudul, hanya diberi nomor, sehingga daftar isinya menampilkan daftar yang mirip dengan daftar ayat-ayat kitab suci. Misalnya, puisi tentang Fransiska yang dinomori 65:98. Maksudnya puisi nomor 65 halaman 98. Belum ada penjelasan penulis tentang hal ini, tapi saya kira ketiadaan judul puisi-puisi ini menyadarkan kita bahwa seringkali tragedi hanya dibaca sebagai angka.
Barangkali bagi sebagian orang, puisi terlalu rumit untuk dimengerti. Bahasa dalam puisi hanya serupa penampilan performatif yang bisa dihayati meski tidak dipahami. Namun, justru karena kebebasan memainkan bahasa, di situlah letak kekuatan puisi. Puisi melawan tanpa kekerasan, berteriak dalam senyap, mampu menusuk tanpa pisau—hanya pakai kata-kata.
Penyair Perempuan dalam Panggung Perlawanan
Dalam sejarah perlawanan terhadap kekuasaan, kita kenal penyair Wiji Thukul dan Soe Hok Gie, dan kita tahu keduanya laki-laki. Lantas, pernahkah kita mendengar penyair perempuan yang melawan?
Di sinilah penyair yang sedang kita bicarakan ini berdiri. Lewat puisi, Cyntha Hariadi menghidupkan kembali Fransiska yang dibunuh negara. Cyntha tidak malu-malu bertutur. Kata-kata dalam puisinya serupa api yang membakar habis upaya negara menghapus sejarah kekerasan seksual yang melukai segenap jiwa perempuan Indonesia, utamanya para perempuan Tionghoa yang saat itu menjadi target khusus pemerkosaan.
Puisi nomor 65 tentang Fransiska terdiri dari sebelas bait, ditulis dalam sudut pandang seorang ibu keturunan Tionghoa yang berbicara kepada anak perempuannya yang berusia 11 tahun.
Bersama dengan petuah dan harapan untuk sang anak, sang ibu membawa ingatan kelam jauh di masa lampau yang menimpa identitasnya; etnis Tionghoa, yang dimanifestasikan dalam kehadiran sosok hantu anak perempuan. Fransiska-lah hantu itu. Hantu korban pemerkosaan yang kemarahannya abadi dalam ingatan perempuan Tionghoa di negara ini.
Inilah potongan bait terakhir puisi tersebut:
usianya sebelas tahun sama dengan kau yang kulahirkan sebelas tahun yang lalu—putri kepompong yang bergulat mencari setitik terang, itik buruk rupa yang belum tahu bahwa ia menawan, kalau saja diberi umur panjang—kami hanya sebuah kulit: perempuan, cina, katolik—fransiska bau cina karena ayahnya peternak babi di Tangerang—fransiska memakai celana pendek dan kaos spice girls—fransiska wangi cina karena punya vagina—negara memperkosanya dengan pecahan mulut botol karena tak punya kontol—
Fransiska berhenti menggerak-gerakkan kepala
Membaca puisi ini rentan memicu perasaan tidak nyaman, baik karena peristiwa yang diangkat maupun karena ketelanjangan bahasanya. Namun, inilah fungsi sastra. Ketika fakta dibungkam, sastra melawan dengan caranya sendiri. Sebab sastra, sekalipun fiksi, berangkat dari realita yang seringkali manusia sangkal.
Keberanian Cyntha Hariadi mengangkat kasus pemerkosaan pada ricuh tragedi Mei 1998 selayaknya kita acungi jempol. Pembaca sastra sudah khatam mengenal Cyntha Hariadi sebagai penulis & penyair yang menulis tentang ketubuhan perempuan.
Sementara bagi awam yang belum mengenal Cyntha Hariadi, saya kira momentum wacana proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia dan pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan kemarin bisa menjadi pintu masuk menyelami penulis perempuan peraih berbagai penghargaan sastra ini.
Buku puisi “CICA” akan membawa kita pada ingatan tentang tragedi pemerkosaan massal 1998. Puisi nomor 65-nya memberitahu kita bahwa ada satu dari sekian nama perempuan yang coba dihapus sejarah kekejaman terhadapnya oleh negara: Fransiska.